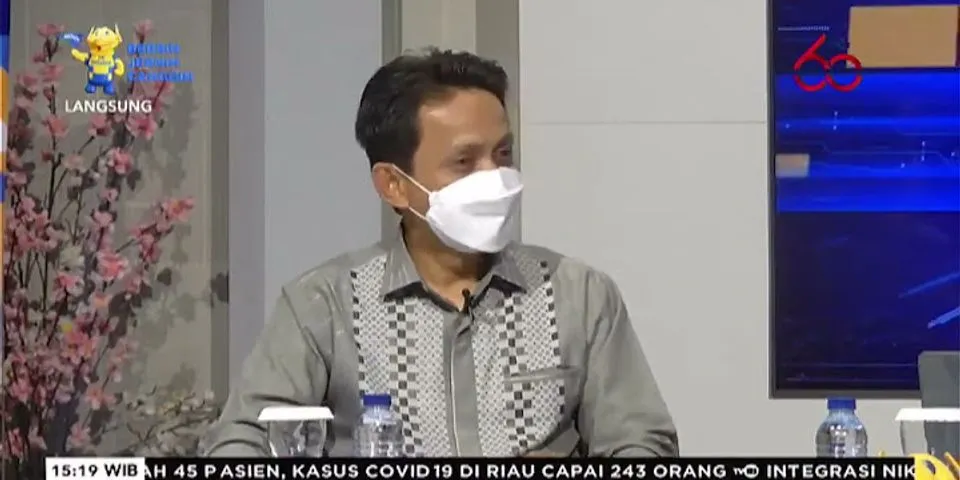Dari tahun ke tahun ilmu pengetahuan terus mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dari tahapan yang paling mitis, pemikiran manusia terus berkembang hingga sampai pada pemikiran yang supra rasional. Atau kalau meminjam terminologi Peursen, dari yang mitis, ontologis hingga fungsional. Sementara menurut Comte, dari yang teologis, metafisik hingga positif. Perkembangan industri di abad 18 yang telah menimbulkan berbagai implikasi sosial dan politik telah melahirkan cabang ilmu yang disebut sosiologi. Penggunaan senjata nuklir sebagaimana pada abad 20 telah melahirkan ilmu baru yang disebut dengan polemologi (Koento Wibisono, 1988:8) dan seterusnya entah apa lagi nanti namanya. Bagi orang Islam, pengetahuan bukan merupakan tindakan atau pikiran yang terpencil dan abstrak, melainkan merupakan bagian yang paling dasar dari kemaujudan dan pandangan dunianya (world-view). Oleh sebab itu tidaklah mengherankan jika ilmu memiliki arti yang demikian penting bagi kaum muslimin pada masa awalnya, sehingga tidak terhitung banyaknya pemikir Islam yang larut dalam upaya mengungkap konsep ini. Konseptualisasi ilmu yang mereka lakukan nampak dalam upaya mendefinisikan ilmu yang tiada habis-habisnya, dengan kepercayaan bahwa ilmu tak lebih dari perwujudan "memahami tanda-tanda kekuasaan Tuhan", seperti juga membangun sebuah peradaban yang membutuhkan suatu pencarian pengetahuan yang komperehensif. Sebagaimana kata Rosentall, sebuah peradaban Muslim tanpa hal itu tak akan terbayangkan oleh orang-orang Islam abad pertengahan sendiri, lebih-lebih pada masa sebelumnya (Anees, 1991:73). Reorientasi intelektual umat Islam harus dimulai dengan suatu pemahaman yang benar dan kritis atas epistemologinya. Dengan begitu, sebuah reorientasi seharusnya bukan merupakan suatu pengalaman yang baru bagi kita, melainkan sekadar sebuah proses memperoleh kembali warisan kita yang hilang. Jika umat Islam tidak ingin tertinggal maju dengan dunia Barat, maka sudah saatnya untuk menghidupkan kembali (revitalisasi) warisan intelektual Islam yang selama ini terabaikan, dan jika perlu mendefinisikan kembali ilmu dengan dasar epistemologi yang diderivasi dari wahyu (baca: Al-Qur'an dan al-Hadis). Seperti kata Anees (1991: 83), pembaruan-pembaruan pendidikan di seluruh dunia Islam saat ini lebih dipacu untuk membangun tiruan-tiruan tonggak intelektual Barat daripada membentuk kembali sumber akalnya sendiri. Jika kita tidak mendefinisikan kembali konsep pandangan dunia (world-view) Islam, maka kita hanya akan menoreh luka-luka intelektual kita sebelumnya. Bukankah sains dan teknologi adalah juga warisan intelektual umat Islam sendiri? Oleh sebab itu kita harus menemukan kembali warisan yang berharga itu. Kita mesti ingat sabda Nabi "Bahwa ilmu pengetahuan (hikmah) adalah perbendaharaan orang mukmin yang telah hilang. Barang siapa menemukannya, maka ia berhak atasnya." (Lihat Al-Qardhawi, 1989 : 56). Dalam konteks ini, negara kita Indonesia termasuk negara yang menempati posisi terbesar jumlah penduduk muslimnya. Tetapi potensi mayoritas muslim tersebut belum menjamin peran sosialnya. Hal ini tentu terkait dengan soal konseptualisasi ilmu dan pendidikan. Apakah pendidikan yang dikembangkan oleh umat Islam Indonesia sudah memenuhi fungsi dan sasarannya?  B. Prinsip Pendidikan Islam Sebagaimana yang diungkap oleh Kuntowijoyo (l994: 350), bahwa pendidikan tinggi Islam saat ini --sebagaimana pendidikan tinggi lainnya-- secara empirik belum mempunyai kekuatan yang berarti karena pengaruhnya masih kalah dengan kekuatan-kekuatan bisnis maupun politik. Disinyalir, bahwa pusat-pusat kebudayaan sekarang ini bukan berada di dunia akademis, melainkan di dunia bisnis dan politik. Dalam setting seperti ini lembaga pendidikan tinggi Islam terancam oleh subordinasi. Pendidikan tinggi Islam, baik dalam konteks nasional Indonesia maupun sebagai bagian dari dunia Islam, kini tengah menghadapi tantangan yang lebih berat. Agenda besar yang dihadapi bangsa Indonesia kini adalah, bagaimana menciptakan negara yang aman, adil dan makmur dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, yang didukung oleh warga negara yang berpengetahuan, beriman dan bertakwa. Dengan begitu maka pendidikan tinggi Islam dituntut untuk berperan serta mewujudkan tatanan Indonesia baru dimaksud, dengan merumuskan langkah-langkah pengembangannya (Zainuddin, 2003: 26 ). Hingga saat ini masih ditengarai bahwa sistem pendidikan Islam belum mampu menghadapi perubahan dan menjadi counter ideas terhadap globalisasi kebudayaan. Oleh sebab itu pola pengajaran maintenance learning yang selama ini dipandang terlalu bersifat adaptif dan pasif harus segera ditinggalkan. Dengan begitu, maka lembaga pendidikan Islam setiap saat dituntut untuk selalu melakukan rekonstruksi pemikiran kependidikan dalam rangka mengantisipasi setiap perubahan yang terjadi. Setidaknya ada tiga faktor yang menjadikan model pendidikan Islam berwatak statis dan tertinggal: pertama, subject matter pendidikan Islam masih berorientasi ke masa lalu dan bersifat normatif serta tekstual. Ini bukan berarti bahwa kita harus meninggalkan warisan masa lalu. Warisan masa lalu sangat berharga nilainya karena ia merupakan mata rantai sejarah yang tidak boleh diabaikan. Prinsip: tetap memelihara tradisi warisan masa lalu yang baik dan mengambil tradisi yang lebih baik (al-muhafadhat ala ‘l-Qadim as-Shalih wa ‘l-akhdzu bi ‘l-Jadid al-Ashlah) justru merupakan prinsip yang tepat bagi sebuah rekonstruksi pemikiran pendidikan Islam; kedua, masih mengentalnya sistem pengajaran maintenance learning yang bercirikan lamban, pasif dan menganggap selalu benar terhadap warisan masa lalu; ketiga masih ada pandangan dikotomis ilmu secara substansial (ilmu agama dan ilmu umum). Secara umum Johan Hedrik Meuleman (Perta, 2002: 16-17) melihat adanya beberapa kelemahan tradisi ilmiah di kalangan Muslim, yaitu pertama, adanya logosentrisme, tektualis. Akibat logosentrisme tersebut kemudian mengabaikan unsur tak tertulis dari agama dan kebudayaan Islam, seperti tindakan sosial, seni dst.; kedua sikap apologetik terhadap aliran (teologi, fiqh dst.); ketiga adanya kecenderungan yang verbalistik dan memberikan wibawa terlalu besar pada tradisi, yang berimplikasi pada sikap ekskulisivisme. Kondisi demikian menurut Meuleman, bebannya masih terasa sampai sekarang ini. Malangnya hal serupa juga dialami oleh Islamolog Barat. Pada sebagian besar masyarakat kita sekarang ini juga masih muncul anggapan, bahwa “agama†dan “ilmu†merupakan entitas yang berbeda dan tidak bisa ditemukan, keduanya dianggap memiliki wilayah sendiri-sendiri baik dari segi objek formal-material, metode penelitian, kriteria kebenaran, peran yang dimainkan oleh ilmuwan maupun status teori masing-masing, bahkan sampai pada penyelenggaraan institusinya. Kenyataan ini bisa kita lihat misalnya pada pemisahan departemen dalam sistem pemerintahan Indonesia (ada departemen agama ada pula departemen pendidikan). Adalah sangat penting untuk melihat sejarah masa lalu, bahwa dalam sejarah kependidikan Islam telah terbelah dua wajah paradigma integralistik-ensiklopedik di satu pihak dan paradigma spesifik-paternalistik di pihak lain. Paradigma pengembangan keilmuan yang integralistik-ensiklopedik ditokohi oleh ilmuwan Muslim, seperti Ibn Sina, Ibn Rusyd, Ibn Khaldun, sementara yang spesifik-paternalistik diwakili oleh ahli hadis dan ahli fiqh. Keterpisahan secara diametral antara keduanya (dikotomis) dan sebab lain yang bersifat politis-ekonomis itu menurut Amin Abdullah (Perta, 2002: 49) berakibat pada rendahnya kualitas pendidikan dan kemunduran dunia Islam saat itu. Oleh sebab itu Amin Abdullah menawarkan gerakan rapproachment (kesediaan untuk saling menerima keberadaan yang lain dengan lapang dada) antara dua kubu keilmuan yang dianggap sebagai sebuah keniscayaan. Gerakan ini juga disebut dengan reintegrasi epistemologi. Di sini pula Brian Fay (1996) menyarankan agar kita waspada terhadap adanya dikotomi, menghindari dualisme buruk dan supaya berpikir secara dialektis. Disarankan oleh Fay, agar kita tidak terjebak pada kategori-kategori yang saling bertolak belakang. Kategori-kategori atau dikotomi-dikotomi itu harus disikapi secara terbuka dan dipikirkan secara dialektis. Dalam perspektif keilmuan Islam, posisi filsafat Islam adalah sebagai landasan adanya integrasi berbagai disiplin dan pendekatan yang makin beragam, karena dalam konstruks epistemologi Islam, filsafat Islam dengan metode rasional-transendentalnya dapat menjadi dasarnya. Sebagai contoh, fiqh pada hakikatnya adalah pemahaman yang dasarnya adalah filsafat, yang kemudian juga dikembangkan dalam ushul fiqh. Tanpa filsafat, fiqh akan kehilangan semangat inovasi, dinamisasi dan perubahan. Oleh karena itu jika terjadi pertentangan antara fiqh dan filsafat seperti yang pernah terjadi dalam sejarah pemikiran Islam, maka menurut Musa Asy’ari (2002: 34), hal ini lebih disebabkan karena terjadinya kesalahpahaman dalam memahami risalah kenabian. Filsafat bukan anak haram Islam, melainkan anak kandung yang sah dari risalah kenabian tersebut. Senada dengan Musa, Nursamad (tt:19-20) berpendapat, bahwa setiap diskursus tentang metodologi haruslah dibangun di atas sentuhan-sentuhan filsafat. Tanpa sense of philosophy menurut Nursamad, maka sebuah metodologi akan kehilangan substansinya. Metodologi Studi Islam (MSI) perlu dikembangkan lebih lanjut agar visi epistemologisnya dapat menjabarkan secara integral dan terpadu tiga arus utama dalam ajaran Islam: aqidah, syari’ah dan akhlaq. Integritas ketiga aspek tersebut hendaknya dimantapkan berdasarkan kecenderungan intelektual masa kini, bukan mencatat metodologi setiap ilmu yang berkembang dalam sejarah pemikiran Islam secara parsial, melainkan berupaya menemukan hubungan-hubungan logis antar pelbagai disiplin ilmu yang berkembang dalam wacana pemikiran Islam kontemporer. Para ilmuwan dulu memang mengklasifikasi ilmu dalam berbagai macam jenis, Ibn Khaldun misalnya membuat klasifikasi ilmu dalam dua jenis ilmu pokok: naqliyah dan ‘aqliyah. Ilmu naqliyah adalah ilmu yang berdasarkan wahyu, dan ilmu aqliyyah adalah ilmu yang berdasarkan rasio. Menurut Khaldun yang termasuk ilmu naqliyah adalah: al-Qur’an, hadis, fiqh, kalam, tasawuf dan bahasa; sedangkan yang termasuk ilmu aqliyah adalah: filsafat, kedokteran, pertanian, geometri, astronomi dst. Tetapi klasifikasi ilmu tersebut menurut Azyumardi Azra (Perta, 2002:16) bukan dimaksud mendikotomi ilmu antara satu dengan yang lain, tatapi hanya sekadar klasifikasi. Klasifikasi tersebut menunjukkan betapa ilmu tersebut berkembang dalam peradaban Islam. Dalam konteks ini ilmu agama Islam merupakan salah sau saja dari berbagai cabang ilmu secara keseluruhan. Jadi persoalannya bukan “ilmu agama†dan “non agamaâ€, tetapi lebih kepada “kepentinganâ€, untuk apa ilmu tersebut digunakan (karena ilmu sebagai instrumen, bukan tujuan). Dan apalagi jika kita sepakat bahwa pada dasarnya sumber ilmu itu dari Allah. Dengan demikian terminologi “ilmu agama†dan “ilmu umumâ€, “non agama†adalah peristilahan sehari-hari dalam pengertian sempit saja. Hanya memang, pertama-tama kita harus punya prioritas bahwa sebagai seorang Muslim harus menguasai ilmu yang berkaitan langsung dengan ibadah mahdhah itu, misalnya ilmu tentang shalat, puasa, zakat, haji dan seterusnya, yang ilmu tersebut sering disebut ilmu syar’iah/ fiqh; dan ilmu tentang ketuhanan/ keimanan kepada Allah SWT, yang biasa disebut sebagai ilmu tauhid/ kalam. Ilmu-ilmu inipun sebetulnya jika dipahami secara mendalam dan kritis tampak sangat berkaitan dan tak terpisahkan dengan ilmu-ilmu yang selama ini disebut “ilmu umum†itu, misalnya ilmu sosial dan humaniora dan juga ilmu alam. Karena semua sistem peribadatan (al-’ibadah, worship) didalam Islam mengandung dimensi ajaran yang tidak lepas dari hubungan antara Allah SWT sebagai Zat pencipta (al-Khaliq) dan manusia atau alam sebagai yang dicipta (al-makhluq). Dan hubungan ini dalam al-Qur’an disebut sebagai hablun min Allah wa hablun min al-nas, hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Di sini rukun iman dalam ajaran Islam lebih berorientasi pada hubungan vertikal, manusia dengan Allah atau yang ghaib, sedang rukun Islam lebih berorientasi pada hubungan horizontal antara manusia dengan manusia yang lain ataupun alam semesta. Tetapi keduanya (iman dan Islam) tak dapat dipisahkan tak ubahnya seperti hubungan ilmu dan amal (integral) Dalam perspektif sejarah, pengadilan inquisi yang dialami oleh baik Copernicus (1543), Bruno (1600) maupun Galileo (1633) oleh geraja karena pendapatnya yang bertolak belakang dengan agama, telah mempengaruhi proses perkembangan berpikir di Eropa, yang pada dasarnya ingin terbebas dari nilai-nilai di luar bidang keilmuan yang berjuang untuk menegakkan ilmu yang berdasarkan penafsiran alam sebagaimana adanya (das sein) dengan semboyan: “ilmu yang bebas nilaiâ€. Setelah pertarungan + 250 tahun, atau yang dikenal dengan gerakan renaissance (abad 15) dan aufklarung (abad 18), para ilmuwan mendapat kemenangannya. Sejak saat itulah filsafat Barat menjadi sangat antrosopentris, terbebas dari ikatan agama dan sistem nilai. Di saat inilah terjadinya benih “sekularisasi†di dunia Barat. Para ilmuwan tidak lagi percaya dengan agama yang dianggap “membelenggu†kemajuan ilmu pengetahuan. Kepercayaan agama luntur karena dianggap tidak mendukung pertumbuhan ilmu dan cara berpikir yang ilmiah. Oleh sebab saatnya kini kita tidak perlu mengulang lagi sejarah kelabu pertentangan antara ilmu dan agama (ilmuwan dan agamawan) yang akan melahirkan sekularisasi. Harus ada sinergi dan integrasi antara ilmu dan agama. Kecenderungan untuk memaksakan nilai-nilai moral secara dogmatik ke dalam argumentasi ilmiah menurut Jujun (1986: 4) hanya akan mendorong ilmu surut ke belakang (set back) ke zaman Pra-Copernicus dan mengundang kemungkinan berlangsungnya inquisi ala Galileo (1564-1642 M) pada zaman modern ini. Begitu juga sebaliknya penulis berkeyakinan, bahwa kecenderungan mengabaikan nilai-nilai moral dalam pengembangan ilmu dan teknologi juga akan menjadikan dishumanisme. Di sinilah perlunya paradigma integralisme dan desekularisasi tadi. Lebih dari itu dalam era modern dan globalisasi ini, kita perlu mengembangkan ilmu agama Islam pada wilayah praksis, bagaimana ilmu-ilmu agama Islam mampu memberikan kontribusi yang paling berharga bagi kepentingan kemanusiaan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan Muslim sebelumnya. Berpadunya aspek idealisme dan realisme atau rasionalisme dan empirisme dalam paradigma keilmuan Islam perlu dikembangkan. Karena menurut pengamatan Amin Abdullah (1992:16), selama ini ruang lingkup filsafat Islam lebih cenderung menitikberatkan pada aspek ontologis dan aksiologis ketimbang epistemologisnya. Dan epistemologi yang dibangunnya memenangkan epistemologi Plato/ Platonisme yang rasionalistik-normatif seperti yang nampak dalam dominasi kalam dan sufisme, katimbang empirisme-historis Aristoteles. Kini saatnya kita harus membangun kultur akademik dan keilmuan yang inklusif dan inovatif serta mengorientasikan pada kehidupan yang bersifat praksis. Kemudian kita juga perlu menciptakan kesadaran untuk berlaku objektif (willingness to be objective). Sikap ini penting, sebab objektivitas merupakan ciri ilmiah. Sikap demikian harus dimiliki oleh seorang ilmuwan. Menurut Archi J. Bahm (1980: 4-9) sikap objektif harus memenuhi syarat-sayarat diantaranya: 1) memiliki sifat rasa ingin tahu terhadap apa yang diselidiki untuk memperoleh pemahaman sebaik mungkin; 2) bisa menerima perubahan (fleksibel, terbuka), artinya jika objeknya berubah, maka seorang ilmuwan mau menerima perubahan tersebut; 3) berani menanggung resiko kekeliruan. Oleh sebab itu trial and error merupakan karakteristik dari seorang ilmuwan; 4) tidak mengenal putus asa, artinya gigih dalam mencari objek atau masalah, hingga mencapai pemahaman secara maksimal; 5) terbuka, artinya selalu bersedia menerima kritik dan saran ilmuwan lain secara lapang dada. Adanya anggapan, bahwa pendidikan Islam masih merupakan subsistem dari sistem pendidikan secara umum haruslah dilihat dalam kapasitas rancang bangun bagi para pakar pendidikan Islam untuk melakukan rekonstruksi pendidikan Islam tersebut. Apa sebenarnya konsep pendidikan Islam untuk mengantisipasi masa depan? B. Antisipasi Masa Depan Merumuskan konsep pendidikan Islam memang bukanlah pekerjaan yang ringan, sebab rumusan tersebut harus mengkaitkan Islam sebagai disiplin ilmu. Dalam upaya merekonstruksi pendidikan Islam, kita perlu memperhatikan prinsip-prinsip pendidikan Islam, yang meliputi: (1) pendidikan Islam merupakan bagian dari sistem kehidupan Islam, yaitu suatu proses internalisasi dan sosialisasi nilai-nilai moral Islam melalui sejumlah informasi, pengetahuan, sikap, perilaku dan budaya, (2) pendidikan Islam merupakan sesuatu yang integrated artinya mempunyai kaitan yang membentuk suatu kesatuan yang integral dengan ilmu-ilmu yang lain, (3) pendidikan Islam merupakan life long process sejak dini kehidupan manusia, (4) pendidikan Islam berlangsung melalui suatu proses yang dinamis, yakni harus mampu menciptakan iklim dialogis dan interaktif antara pendidik dan peserta didik, (5) pendidikan Islam dilakukan dengan memberi lebih banyak mengenai pesan-pesan moral pada peserta didik. Prinsip-pinsip di atas akan membuka jalan dan menjadi fondasi bagi terciptanya konsep pendidikan Islam. Dengan tawaran prinsip inilah, konsep pendidikan Islam lebih pas apabila diletakkan dalam kerangka pemahaman, bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan menurut Islam, bukan pendidikan tentang Islam. Pendidikan Islam hendaknya bukan saja berusaha meningkatkan kesadaran beragama, melainkan juga untuk melihat perubahan-perubahan sosial dalam perspektif transedental, dan menempatkan iman sebagai sumber motivasi perkembangan dalam menyelami dan menghayati ilmu pengetahuan modern (Soedjatmoko, 1987). Ini berarti bahwa dalam proses pendidikan Islam terkandung upaya peningkatan kemampuan mengintegrasikan akal dengan nurani dalam menghadapi masalah perubahan sosial. Dengan begitu diharapkan pendidikan Islam dapat memenuhi fungsi yang luhur dalam menghadapi perkembangan sosial, apabila dalam proses belajar-mengajar menggunakan pola pengajaran innovative learning, yakni: (1) berusaha memupuk motivasi yang kuat pada peserta didik untuk mempelajari dan memahami kenyataan-kenyataan sosial yang ada, (2) berusaha memupuk sikap berani menghadapi tantangan hidup, kesanggupan untuk mandiri dan berinisiatif, peka terhadap kepentingan sesama manusia dan sanggup bekerja secara kolektif dalam suatu proses perubahan sosial.  Dalam al-Qur’an Allah berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaknya setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok†(QS. Al-Hasyr: 18). Pesan Tuhan ini bisa dipahami bahwa untuk menuju kemasa depan yang lebih baik, seseorang haruslah memperhatikan apa yang telah dan sedang terjadi di masyarakat. Tentu ini terkait dengan upaya menyadap sebanyak mungkin informasi, kemudian menganalisisnya. Heteroginitas informasi yang telah disadap yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengolahan dan interpretasi akan menumbuhkan kemampuan berpikir secara holistik dan integratif. Bila kemampuan ini telah dimiliki seseorang, maka untuk mengantisipasi perubahan yang menumbuhkan kesadaran internal dan ketrampilan memecahkan masalah bukannya sesuatu yang memberatkan. Adalah bukan tidak mungkin, bahwa persoalan informasi mempunyai korelasi akseptabilitas dengan dunia pendidikan (baca:pendidikan Islam), bahkan dengan fungsi informasi, pendidikan Islam akan mampu mengimbangi kemajuan zaman. Korelasi ini terletak pada persoalan substansi materi pendidikan Islam itu sendiri. Dalam spektrum yang lebih makro, seberapa jauh alih nilai moral mampu membekali peserta didik untuk menghadapi sekaligus memecahkan persoalan secara proporsional sekaligus mampu mengembangkan budaya religius. Spektrum tersebut menuntut peran pendidik (guru, dosen) untuk mampu tampil lebih profesional di hadapan peserta didik dengan menyertakan menu-menu materi yang bersifat kontekstual, dinamis dan berorientasi ke masa depan. Semua ini akan didapatkan jika tradisi menyadap banyak informasi menjadi tuntutan setiap saat bagi para pendidik. Pendidikan sebagai proses penyiapan peserta didik agar memiliki kemampuan mengantisipasi persoalan hari ini dan esok harus dilihat dari dimensi informasi. Dengan kata lain, kemampuan tersebut akan dicapai hanya melalui intensitas mencari, mengolah dan mengintepretasikan informasi. Menguasai informasi hari ini berarti mampu menguasai informasi hari esok. Menguasai permasalahan hari ini berarti menguasai permasalahan hari esok. Sekarang dan esok sebenarnya bersifat saling berkaitan dan merupakan jaringan-jaringan masalah yang kompleks meski dengan tingkat kompleksitas yang beragam. Dengan gelombang informasi, maka proses belajar-mengajar akan terhindar dari diskontinuitas kesejarahan dan sistem nilai dalam pendidikan kemarin, sekarang dan esok. Sehingga pendidikan sebagai alih nilai (transfer of value) tidak hanya memberi materi sesuai dengan program of studies yang ada dalam jadwal kelas, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana mengkondisikan lingkungan yang memungkinkan dirinya secara optimal dan menjadi berkualitas tinggi sesuai tuntutan zaman. Adalah benar apa yang dideskripsikan oleh H.A.R Gibb (seperti yang dikutip Abdussalam, 1983: 17), bahwa tumbuh suburnya sains dalam masyarakat Islam lebih banyak tergantung pada dukungan penguasa. Di mana masyarakat Islam mengalami kemunduran, di situ sains kehilangan vitalitas dan kekuatan. Tetapi selama di salah satu negara masih terdapat penguasa yang masih memberi dukungan pada sains, maka obor ilmu akan tetap menyala. Jika tidak maka akan terjadi kemerosotan intelektual. Indikasi dari situasi ini nampak dalam peristiwa peledakan observatorium bintang di Istambul oleh meriam-meriam angkatan laut atas perintah Sultan Murad III pada abad ke-16, dengan alasan bahwa tugas observatorium untuk mengoreksi jadwal astronomi Ulugh Beg telah selesai, yang lantas dianggap tidak perlu lagi (Abdussalam, 1983 : 17). Pertanyaan selanjutnya adalah, dapatkah kita memimpin kembali di bidang sains? Dengan optimis Abdussalam menjawab, bisa! asalkan katanya, masyarakat secara keseluruhan, terutama generasi mudanya, bersedia menerima kenyataan sebagai tujuan yang diidam-idamkan. Generasi muda harus didorong untuk berpikir ilmiah, mengejar sains dan teknologi dengan menggunakan satu sampai dua persen Pendapatan Nasional untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, paling sedikit sepersepuluhnya. Hal demikian telah dilakukan oleh Jepang ketika revolusi Maiji. Kaisar Jepang bersumpah akan mencari ilmu pengetahuan dari manapun datangnya meski dari sudut bumi ini. Hal yang sama juga dilakukan oleh Uni Sovyet empat puluh tahun lalu, ketika Akademi Ilmu Pengetahuan berambisi untuk unggul dalam sains. Dan langkah ini pula lah yang ditiru secara berencana oleh RRC yang hendak bersaing dengan Inggris Raya (Abdussalam, 1983 : 19 – 20). Persoalan sains dan teknologi begitu pentingnya, hingga Sultan Takdir Alisyahbana (1992) menghimbau, untuk menghadapi masa depan umat manusia, bangsa Indonesia harus meningkatkan kemampuan sains dan teknologi, dengan jalan menyediakan dana sebanyak mungkin untuk mengirimkan generasi muda ke luar negeri, ke pusat-pusat ilmu pengetahuan. Dan cara lain menurut Takdir adalah menterjemahkan karya-karya sains dan dan teknologi tersebut. Dia mencontohkan ketika Jepang belum maju seperti sekarang, mereka berusaha menterjemahkan buku-buku berbahasa asing. Sejak 150 tahun yang lalu orang Jepang sudah melakukan penterjemahan sekitar 2000 hingga 2500 buku setiap tahunnya. Dan sekarang Malaysia sudah mampu mengirimkan mahasiswanya ke luar negeri sekitar 7000 setiap tahun. Jalan lain untuk menumbuhkan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi adalah menjadikan kampus sebagai pusat riset dan pengembangan ilmiah. C. Tanggungjawab Ilmuwan MuslimMasalah sentral yang perlu segera digarap, menyangkut angkatan muda di dunia Islam menurut Hussein Nasr (1989 : 6) adalah: Pertama, bagaimana memberikan bekal yang cukup untuk mereka, bagaimana memahamkan pesan-pesan Islam secara tepat dan benar; kedua, memberikan pengertian kepada mereka betapa kaya khazanah intelektual dan tradisi spiritual Islam. Jangan membiarkan mereka terperangkap oleh slogan dan gelombang peradaban Barat yang sekuler. Dengan kata lain kita berharap untuk bisa mencetak generasi pemikir Islam yang handal yang memiliki wawasan luas dan jauh ke depan, bukan generasi yang jumud dan fantastis. Kita telah memiliki tradisi keilmuan yang sudah berusia 14 abad, yang berisi ajaran-ajaran komprehensif tentang bagaimana kita harus berhubungan dengan Tuhan (teologis), dengan sesama manusia dan juga alam semesta (antropologis-kosmologis). Tradisi keilmuan dengan bimbingan wahyu harus dihidupkan kembali untuk menjawab tantangan modernitas. Umat Islam dengan pandangan dunianya sendiri kata Anees (1991: 83), memiliki dua tanggung jawab. Pertama, membuat dan menghasilkan dasar ilmunya sendiri, yang merupakan sebuah sistem untuk menghasilkan pengetahuan pribumi yang organis; kedua, tanggung jawab moral terhadap umat manusia dan alam untuk menjamin bahwa keduanya berada pada kondisi kesejahteraan material dan spritual yang terbaik. Sebagaimana kata Syah Idris (dalam Budiman, 1988: 12–13), bahwa baik pakar ilmu pengetahuan alam maupun sosial muslim sama-sama dibebani kewajiban untuk merumuskan konsep sains yang baru dan radikal. Tugas tersebut menurut Idris adalah: Pertama, menunjukkan eksistensi Allah SWT bukan semata-mata sebagai masalah keimanan yang taken for granted, tetapi juga fakta yang kebenarannya dapat dibuktikan secara rasional; kedua, memikirkan konsekuensi praktis dari pandangan tentang sains yang lebih menyeluruh dan lebih luas. Setiap ahli dibebani untuk melakukan revisi atas sains berdasarkan spesialisasi masing-masing. Jika kita berhasil melakukan upaya tersebut, maka kita dapat membuktikan bahwa sains Islam memiliki landasan yang kokoh dan memiliki kebenaran yang dapat dibuktikan secara rasional. Karena ilmuwan Muslim sebagai pewaris Nabi (waratsat al-anbiya'), maka ia memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar. Tugas ilmuwan muslim tersebut menurut penulis adalah: Pertama, sebagai saksi (terhadap perbuatannya sendiri maupun orang lain). Sebagai saksi ia dituntut untuk adil dan jujur; kedua, penyeru ke jalan Allah dan petunjuk ke jalan yang benar, amar ma'ruf nahi munkar (lihat QS. Al-Ahzab: 45–46); ketiga, sebagai khalifah Allah di bumi. Karena sebagai hamba yang dipercayai oleh Tuhan, maka ia harus bertanggung jawab atas amanat yang dipikulkan. Dalam Islam, startegi pengembangan ilmu juga harus didasarkan pada perbaikan dan kelangsungan hidup manusia untuk menjadi khalifah di bumi dengan tetap memegang amanah besar dari Allah SWT. Oleh sebab itu ilmu harus selalu berada dalam kontrol iman. Ilmu dan iman menjadi bagian yang integral dalam diri seseorang, sehingga dengan demikian teknologi sebagai produk dari ilmu akan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi manusia di sepanjang masa. Dan inilah yang mesti menjadi tanggung jawab ilmuwan muslim dalam mengembangkan ilmu. Kini kita harus berpikir terus tentang kelangsungan perkembangan ilmu, lebih-lebih ilmu sebagai proses yang menggambarkan aktivitas manusia dan masyarakat ilmiah yang sibuk dengan kegiatan penelitian, eksperimentasi, ekspidisi dan seterusnya untuk menemukan sesuatu yang baru. Formulasi-formulasi yang telah diperkenalkan oleh para ilmuwan pendahulu kita hendaknya diaktualisasikan untuk kemudian dikembangkan lebih lanjut, atau bahkan perlu improvisasi. Oleh sebab itu proses pendidikan tak boleh tidak harus digalakkan terus dalam berbagai disiplin ilmu. Proses pendidikan inilah yang oleh Islam selalu ditekankan (lihat, Q.S Ali Imran: 190), dan belajar terus menerus sepanjang hidup (life long-education ) seperti yang disebut dalam kata hikmah uthlub al-'Ilma min al-mahdi ila 'l-lahdi, carilah ilmu dari buaian hingga ke liang kubur.  D. Kesimpulan Pengembangan pendidikan agama Islam memerlukan upaya rekonstruksi pemikiran kependidikan dalam rangka mengantisipasi setiap perubahan yang terjadi: pertama, subject matter pendidikan Islam harus berrientasi ke masa depan; kedua, perlu dikembangkan sikap terbuka bagi transfer of knowledge dan kritsis terhadap setiap perubahan; ketiga menjauhkan pandangan dikotomis terhadap ilmu (ilmu agama dan ilmu umum), tidak terjebak pada kategori-kategori yang saling bertolak belakang. Kategori-kategori atau dikotomi-dikotomi itu harus disikapi secara terbuka dan dipikirkan secara dialektis. Karena “agama†dan “ilmu†merupakan entitas yang menyatu (integral) tak dapat dipisahkan satu sama lain. Setiap diskursus tentang metodologi memerlukan sentuhan-sentuhan filsafat. Tanpa sense of philosophy maka sebuah metodologi akan kehilangan substansinya. Metodologi Studi Islam (MSI) perlu visi epistemologis yang dapat menjabarkan secara integral dan terpadu terhadap tiga arus utama dalam ajaran Islam: aqidah, syari’ah dan akhlaq. Kecenderungan untuk memaksakan nilai-nilai moral secara dogmatik ke dalam argumentasi ilmiah hanya akan mendorong ilmu surut ke belakang (set back) ke zaman Pra-Copernicus dan mengundang kemungkinan berlangsungnya inquisi ala Galileo (1564-1642 M) pada zaman modern ini. Begitu juga sebaliknya bahwa kecenderungan mengabaikan nilai-nilai moral dalam pengembangan ilmu dan teknologi juga akan menjadikan dishumanisme. Di sinilah perlunya paradigma integralisme dan desekularisasi terhadap ilmu. Lebih dari itu dalam era modern dan globalisasi ini, kita perlu mengembangkan ilmu agama Islam pada wilayah praksis, bagaimana ilmu-ilmu agama Islam mampu memberikan kontribusi yang paling berharga bagi kepentingan kemanusiaan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan Muslim sebelumnya.DAFTAR PUSTAKA Abdullah, Amin. 1992. Aspek Epistemologi Filsafat Islam, makalah, Yogyakarta: IAIN. Abdussalam .1983. Sains dan dunia Islam, terj. Baiquni, Bandung: pustaka. Al-Qardhawi, Yusuf. 1989. Ar-Rasul wal 'ilm, terjemahan, Kamaluddin A. Marzuki, Bandung, CV. Rosda. Anees, Munawar Ahmad. 1991. “Menghidupkan Kembali Ilmu†dalam Al-Hikmah, Juranal Studi-studi Islam, Juli-Oktober, Bandung: Yayasan Mutahhari. Asy’ary, Musa. 2002. Filsafat Islam: Sunnah Nabi dalam Berpikir. Yogyakarta: LESFI. Departemen Agama RI. 1989. Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta. Fay, Brian. 1996. Contemporary Philosophy of Social Science. Blackwell Publishers, Oxford Kuntowijoyo. 1991. Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi, Bandung: Mizan. Nasr, Seyed Hussein.1989. "Masa Depan Islam", dalam Inovasi, Yogyakarta, UMY Nursamad (tt). Epistetemologi Ilmu Islam, makalah. Soeriasumantri, Jujun S. 1986. Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Soedjatmoko. 1987. Etika Pembebasan, Jakarta: LP3ES. Wibisono, Koento. 1988. Beberapa Hal Tentang Filsafat Ilmu: Sebuah Sketsa Umum Sebagai Pengantar Untuk Memahami Hakekat Ilmu dan Kemungkinan Pembangunannya, Yogyakarta: IKIP. Zainuddin, M. 2003. Filsafat Ilmu: Perspektif Pemikiran Islam. Malang, Bayumedia. -----------------. 2002, “Reformasi Perguruan Tinggi (Bukan Lagi Berorientasi Bisnis)†dalam Jawa Pos, Kamis 15 Agustus.  Jurnal dan Surat Kabar: Harian Pelita, 3 Agustus1992. Jurnal Studi Islam, Juli-Oktober Bandung, Yayasan Muthahhari, 1991. Jurnal Komunikasi Perguruan Tinggi, Perta, 2002.(Author) |

Pos Terkait
Periklanan
BERITA TERKINI
Toplist Popular
#2
#4
#6
#8
Periklanan
Terpopuler
Periklanan
Tentang Kami
Dukungan

Copyright © 2024 idkuu.com Inc.