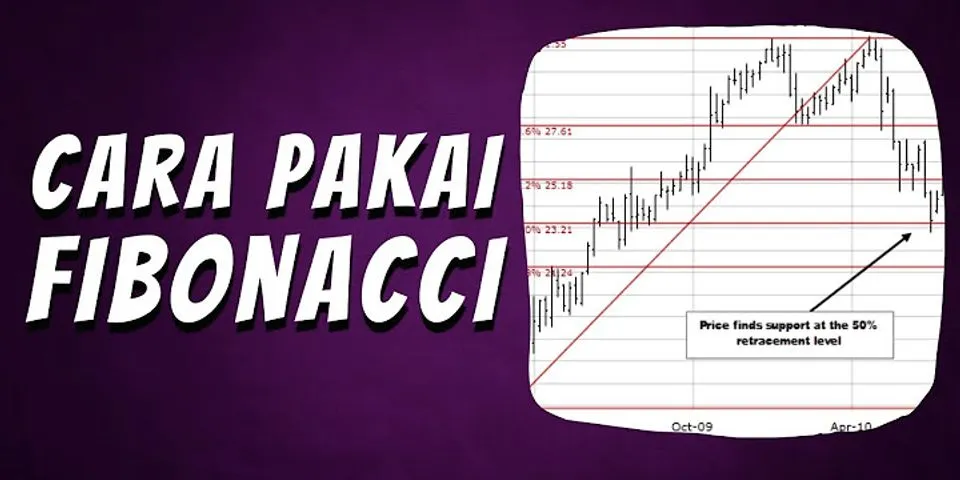tirto.id - Auguste Comte (1798-1857) adalah seorang filsuf asal Prancis yang sering kali disebut sebagai peletak dasar ilmu sosiologi. Ia juga turut memperkenalkan istilah “Sociology". Istilah itu pertama kali diperkenalkan pada tahun 1838 dalam bukunya yang berjudul Cours De Philosophie Positive. Dalam karyanya tersebut, Comte menjelaskan bahwa kata “sosiologi" berasal dari bahasa Latin yaitu “socius" yang berarti "kawan atau teman", dan “logos" yakni "ilmu pengetahuan". Dengan demikian, sosiologi merupakan satu cabang ilmu yang mempelajari masyarakat, termasuk perilaku masyarakat, dan perilaku sosial manusia dengan jalan mengamati perilaku kelompok yang dibangunnya. Kelompok tersebut mencakup keluarga, suku bangsa, negara, dan berbagai organisasi politik, ekonomi, sosial.
Melalui buku itu pula, Comte mengenalkan tahap perkembangan intelektual, yang masing-masing merupakan perkembangan dari tahap sebelumya. Tiga tahapan itu meliputi: a) Tahap Teologis, yakni tingkat pemikiran manusia bahwa semua benda di dunia mempunyai jiwa dan itu disebabkan oleh suatu kekuatan yang berada di atas manusia; b) Tahap Metafisis, yang pada tahap ini manusia menganggap bahwa di dalam setiap gejala terdapat kekuatan-kekuatan atau inti tertentu yang pada akhirnya akan dapat diungkapkan; serta c) Tahap Positif, yaitu tahap di mana manusia mulai berpikir secara ilmiah.
Tiga tahap perkembangan intelektual yang terakhir, atau Tahap Positif, pada akhirnya membawa manusia mengenal pemikirannya yang mahsyur: Positivisme.
Mengenal PositivismeDalam ilmu pengetahuan, positivisme merupakan bentuk pemikiran yang menekankan pada aspek faktual pengetahuan, khususnya pengetahuan ilmiah. Umumnya positivisme menjabarkan pernyataan faktual pada suatu landasan pencerapan (sensasi). Dengan kata lain, positivisme merupakan aliran pemikiran yang menyatakan bahwa ilmu-ilmu alam (empiris) sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak nilai kognitif dari studi filosofis atau metafisik. Menurut Anthony Flew dalam A Dictionary of Philosophy (1984), jika dilihat dari asal perkembangannya, positivisme merupakan paham falsafah dalam alur tradisi Galilean yang muncul dan berkembang pada abad XVIII. Comte sendiri telah mencoba menggunakan paradigma Galilean untuk menjelaskan kehidupan manusia dalam masyarakat. Menurut Comte, konsep dan metode ilmu alam dapat dipakai untuk menjelaskan kehidupan kolektif manusia. Selanjutnya dikatakan bahwa kehidupan manusia juga terjadi di bawah imperative hukum sebab-akibat dengan segala kondisi dan faktor probabilitasnya. Sebagaimana kejadian di alam semesta yang tunduk pada hukum yang bersifat universal, Comte menyatakan bahwa kehidupan manusia selalu dapat dijelaskan sebagai proses aktualisasi hukum sebab-akibat. Setiap kejadian atau perbuatan dalam kehidupan manusia yang kasuistik sekalipun selalu dapat dijelaskan dari sisi sebab-akibat yang rasional dan alami dan karena itu bersifat ilmiah (scientific). Menurutnya, setiap perbuatan tidak dapat dimaknakan dari substansi yang berupa niat dan tujuannya sendiri yang moral-altruistik dan yang metafisikal. Sebab, yang demikian itu merupakan sesuatu yang dapat dianggap tidak ilmiah (unscientific).
Kelebihan dan Kekurangan PositivismeSebagai sebuah pemikiran, positivisme memiliki kelebihan dan kekurangan. Mengutip Jurnal Cakrawala (2016), positivisme memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai berikut: a.) Kelebihan
b.) Kekurangan
Baca juga:
Baca juga
artikel terkait
TEORI SOSIOLOGI
atau
tulisan menarik lainnya
Ahmad Efendi
Subscribe for updates Unsubscribe from updates
KITAB AL-RISA<LAH DALAM TILIKAN POSITIVISME HUKUM Abdul Mun’im, Lukman Santoso, Niswatul Hidayati ABSTRAK Penelitian ini merupakan penelitian literatur dengan pendekatan kualitatif-filosofis. Dari hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa: Pertama, Menurut al-Sha>fi’i<, hakikat hadirnya hukum adalah kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Hukum Islam dipahami al-Sha>fi’i< sebagai institusi yang tidak berakar maupun dicangkokkan pada sosiologi sebagaimana positivisme hukum. Hukum Islam merupakan sarana mengabdi kepada Tuhan, dan bukan kepada masyarakat, meskipun pada aspek teknisnya sangat memahami kondisi masyarakat. Kedua, Al-Sha>fi’i< membangun teori hirarkhi hukum Islam didasarkan pada empat sumber yaitu, al-Qur’an, sunnah Nabi, konsensus ulama (ijma’), dan metode analogi (qiyas). Jika ditilik secara konseptual dari perspektif positivisme hukum, maka teori sumber hukum Islam yang dibangun oleh al-Sha>fi’i< kurang lebih sama dengan teori tingkatan norma Hans Kelsen. Ketiga, Dalam konteks eksistensi positivisme hukum ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia selaku anggota masyarakat agar tercipta kepastian hukum. Tentu eksistensi ini berbeda dalam sistem hukum Islam, hukum hadir dalam Islam untuk mengatur kehidupan manusia, baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat agar dapat bertingkah laku yang sesuai dengan kehendak Sang pencipta. Keempat, Sumber positivisme hukum yang terbagi dalam hukum material dan formal juga memiliki aspek perbedaan dengan hukum Islam. Hukum Islam juga mempunyai sumber hukum material, namun memiliki substansi berbeda dengan positivisme, yaitu bahwa sumber hukum Islam berasal dari wahyu, sedangkan hukum positif bersumber kepada perilaku dan realitas dalam masyarakat. Kata Kunci: Hukum, Positivisme Hukum, al-Risa>lah, al-Sha>fi’i< PENDAHULUAN Urgensi epistemologi us}u>l al-fiqh dalam ranah pemikiran Hukum Islam, tampaknya baru dirasakan seiring dengan perkembangan zaman yang semakin pesat. Penyebaran Islam yang semakin meluas ke berbagai daerah, serta penetrasi budaya non-Arab, hal inilah yang sedikit banyak mempengaruhi perkembangan penafsiran terhadap teks wahyu. Di tengah kegelisahan akademik ini, al-Ima>m al-Sha>fi’i< (w. 204 H) kemudian hadir dengan mengusung teori-teori ilmu fiqh yang dibutuhkan. Dengan bekal pengetahuan yang memadai terhadap eksistensi kedua kubu pemikiran yang saling berhadap-hadapan saat itu, al-Sha>fi’i< lalu dapat memadukan penggunaan sumber ajaran suci yang berupa teks dengan kemampuan rasio secara bersamaan. Kitab al-Risa>lah adalah salah satu karya al-Ima>m al-Sha>fi’i< yang monumental dalam bidang us}u>l al-fiqh.1 Karya ini dipandang sebagai karya pertama yang dikenal dalam bidang us}u>l al-fiqh.2 Disebutkan juga bahwa al-Sha>fi’i> datang dalam suasana kebingungan epistemologis, ketika para 1 Kitab ini merupakan karya al-Ima>m al-Sha>fi’i< atas permintaan Abdurrahman bin Mahdi yang berkaitan dengan penjelasan makna-makna al-Qur’an, dan menghimpun beberapa khabar, ijma’ dan penjelasan tentang nasikh dan mansukh dalam al-Qur’an dan sunnah. Dan juga atas dorongan dari Ali bin al-Madani agar al-Ima>m al-Sha>fi’i memenuhi permintaan Abdurrahman bin al- Mahdi. Atas permintaan dan dorongan itulah Imam Syafi’i menulis kitab ar-Risa>lah ini. Lihat Ar-Risa>lah Imam Syafi’i. terj. Misbah, (Jakarta; Pustaka Azzam, 2008), 13. 2 ‘Abdulla>h bin Sa’i<d Muh}ammad ‘Abba>di< al-Lah{ji< al-Sah{a>ri<, I<d}a>h al-Qawa>’id al-Fiqhi<yah (Surabaya: al- Hidayah, 1410 H.), 2.
2 Abdul Mun’im, Lukman Santoso, Niswatul Hidayati Kodikasia, Volume, 12 No. 1 Tahun 2018 yuris Islam sempat beberapa saat sebelumnya terbelah ke dalam dua kecenderungan utama, yaitu ahl al-h}adi<th dan ahl al-ra’y. Selain appreciate terhadap penggunaan al-Sunnah sebagai sumber inspirasi hukum, sebagaimana ditunjukkan kubu tradisionalis (ahl al-h}adi<th), al-Sha>fi’i< juga tidak dapat menafikan apa yang menjadi komitmen kalangan rasionalis (ahl al-ra’y) dalam penggunaan analogi. Kedatangan al-Sha>fi’i< menenteramkan persengketaan antara kedua golongan tersebut dan secara perlahan namun pasti, pemikiran dalam hukum Islam menapak jalan yang telah digariskannya. Tidak hanya di kalangan madhab Shafi’i<, tetapi arahannya juga diikuti semua madhab hukum dalam Islam.3 Us}u>l al-fiqh adalah salah satu bidang ilmu agama Islam yang lebih kurang berarti metodologi hukum Islam. Ilmu ini juga dapat disebut metodologi riset menemukan hukum Islam. Us}u>l al-fiqh juga merupakan sistem interpretasi. Sebagaimana layaknya sebuah sistem interpretasi, us}u>l al-fiqh juga berdiri di atas premis-premis yang dianggap benar. Dengan demikian, al-Risa<lah diketahui menjelaskan premis-premis itu sebagai pijakan dari sistem interpretasi yang ditawarkannya. Berkat inisiasi dari al-Sha>fi’i< berupa diterimanya al-Risa>lah secara luas di kalangan umat Islam, ia dijuluki sebagai “Bapak us}u>l al-fiqh”. Selanjutnya berkat ketentraman epistemologis yang tercipta berkat al-Risa>lah, ia juga dikenal sebagai “Bapak equilibrium” dalam Islam. Equilibrium atau keseimbangan yang tercipta itu adalah antara kecenderungan ahl al-h}adi<th dan ahl al- ra’y di atas. Artinya kedua kecenderungan itu menjadi mendekat dan mencapai kesepakatan- kesepakatan atas posisi-posisi yuristik dalam pemikiran hukum Islam.4 Banyak pernyataan al-Sha>fi’i< yang berlaku sebagai premis-premis utama dari metolodologi hukum yang ditawarkannya yang patut ditilik dari sudut pandang positivisme hukum. Al-Sha>fi’i< mengatakan bahwa kasus apa saja pasti ada penyelesaiannya di dalam al-Qur’an: (Tidak ada kasus hukum yang terjadi pada para pemeluk agama Allah kecuali pasti ada dalil penyelesaiannya dalam bentuk petunjuk) Pernyataan senada diulanginya lagi di bagian lain: (Setiap kasus hukum yang terjadi di kalangan orang Islam pasti ada keputusan yang pasti. Dalam keadaan demikian, ia harus mengikutinya apa adanya. Bisa juga harus ditemukan dahulu dalil yang sebenarnya sudah pasti ada. Di sini caranya adalah dengan ijtiha>d, sedangkan ijtiha>d itu adalah qiya>s). Di sini al-Sha>fi’i< menegaskan bahwa apa yang disebut hukum adalah yang tercantum di dalam al-Qur’an. Sedangkan satu-satunya pengembangan yang sah dari makna apa yang terkandung di dalam al-Qur’an adalah qiya>s atau analogi. Dalam pikiran al-Sha>fi’i<, orang Islam tidak dibenarkan mencari hukum di luar al-Qur’an. Orang Islam meyakini bahwa al-Qur’an adalah firman Allah, atau kata-kata Allah sendiri. Di dalam wacana us}u>l al-fiqh, Allah disebut sebagai al-Sha>ri’, yang dalam literatur us}ul al-fiqh berbahasa Inggris diterjemahkan dengan The Lawgiver. 3 Imran Ahsan Khan Nyazee, Theories of Islamic Law (Islamabad: The International Institute of Islamic Thought, 1994), 52; Kemal A. Faruki, Islamic Jurisprudence (Delhi: Adam Publisher & Distributors, 1994), 22-23. 4 Ahmad Hasan, “Al-Sha>fi’i<’s Role in the Development of Islamic Jurisprudence,” Islamic Studies, 5 (1966), 239; Abdul Mun’im Saleh, Otoritas Maslahah dalam Madhhab Syafi’I (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2012), 31. 5 Muh}ammad bin Idri>s al-Sha>fi’i<, al-Risa>lah ed. Ah}mad Muh}ammad Sha>kir (T.t: Da>r al-Fikr, t.t.), 20. 6 Ibid., 477.
Kitab Al-Risa<lah Dalam Tilikan Positivisme Hukum 3 Kodikasia, Volume, 12 No. 1 Tahun 2018 Dari segi inilah tampaknya premis al-Sha>fi’i< bersentuhan dengan aliran Positivisme Hukum yang mengatakan bahwa hukum adalah perintah. Tidak ada kebutuhan untuk menghubungkan hukum dengan moral, hukum sebagaimana diundangkan, ditetapkan, positum, harus senantiasa dipisahkan dari hukum yang seharusnya diciptakan, yang diinginkan.7 Positivisme Hukum melihat sistem hukum adalah sistem tertutup yang logis, yang merupakan putusan-putusan yang tepat yang dapat dideduksikan secara logis dari aturan-aturan yang sudah ada sebelumnya.8 Hukum adalah perintah dari sang Penguasa Hukum (command of Lawgivers).9 Dengan demikian, hukum sangat ditentukan oleh pertanyaan bagaimana manusia melihat dan menggunakannya. Pada kenyataannya, beragam teori hukum yang berkembang selama ini bertumpu kepada kedua faktor tersebut. Oleh karena itu, jika bandul sebuah teori hukum bergeser ke arah manusia maka teori tersebut memberikan ruang cukup banyak pada faktor manusia. Sebaliknya jika bandul teori tadi banyak bergeser ke arah hukum maka teori tersebut akan menganggap hukum sebagai sesuatu yang mutlak, otonom, dan final. Pengkutuban teori hukum ini pada gilirannya sangat berimplikasi pada lahirnya aliran-aliran hukum dengan berbagai jenis dan karakternya. Dalam konteks tersebut, penelitian ini akan melihat medan persentuhan antara premis-premis al-Sha>fi’i< di dalam al-Risa<<lah dan premis-premis aliran Positivisme Hukum. Terlebih, dewasa ini wacana hakikat hukum dikuasai oleh dua aliran saja, yaitu aliran hukum kodrat dan positivisme. Penelitian ini memilih tilikan positivisme karena aliran ini lebih dominan dalam mendominasi wacana hakikat hukum saat ini. Mengingat setiap aliran filsafat hukum selalu memiliki kelemahan di samping kelebihannya, maka membiarkan sebuah aliran hukum mendominasi wacana bukanlah tindakan yang tepat, dan pasti tidak memuaskan. al-Sha>fi’i< telah memuaskan pertikaian epistemologi dan menciptakan equilibrium. Tetapi banyak pernyataannya yang memiliki kesamaan dengan premis-premis positivisme. Mungkin saat ini positivisme memang paling memuaskan, tetapi dengan perkembangan yang ada, tampaknya positivisme juga tampak cacat epistemologinya, sehingga muncul kritik dari banyak pakar. Berpijak pada hal inilah, mungkin terdapat premis yang lain lagi yang dimiliki al-Sha>fi’i<, sehingga menjadi urgen untuk dikaji lebih mendalam. Sehingga penelitian ini menjadi menarik, untuk menggali apakah hakikat hukum menurut al-Sha>fi’i< dalam al-Risa>lah ? Apakah sumber hukum menurut al-Sha>fi’i< di dalam al-Risa>lah, dan bagaimana hirarkinya serta bagaimana bangunan metodologi menemukan hukum? Bagaimana sikap al-Sha>fi’i< di dalam al-Risa>lah terhadap hal-hal yang bersifat non-hukum (metayuridis)? Serta Apakah al-Shafi’i< dalam al- Risa>lah mempersoalkan tujuan hukum? PEMBAHASAN Teori Positivisme Hukum Positivisme adalah aliran filsafat yang berpangkal dari fakta yang positif-empiris. Sesuatu yang di luar fakta atau empiris dikesampingkan dalam pembicaraan filsafat dan ilmu pengetahuan.10 Pada dasarnya positivisme bukanlah suatu aliran yang berdiri sendiri. Ia hanya menyempurnakan empirisme dan rasionalisme yang bekerja sama. Dengan kata lain, ia menyempurnakan metode ilmiah (scientific methods) dengan memasukkan perlunya eksperimen dan ukuran-ukuran. Jadi pada dasarnya positivisme itu sama dengan empirisme ditambah rasionalisme. Hanya saja pada 7 http://www.boyyendratamin.com/ 2011/08/ positivisme-hukum-di-indonesia-dan.html, diakses tanggal 14 Maret 2016. 8 Ibid. 9 Ibid. Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Sampai Postmoderisme) (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2011), 158. 10 Juhaya S. Praja, Aliran-Aliran Filsafat dan Etika. cet. Ke-2. (Jakarta: Kencana, 2005).
4 Abdul Mun’im, Lukman Santoso, Niswatul Hidayati Kodikasia, Volume, 12 No. 1 Tahun 2018 empirisme dapat menerima pengalaman bathiniah sedangkan pada positivisme membatasi pada perjalanan objektif saja.11 Positivisme berkembang dalam sistem hukum Eropa kontinental (civil law) abad XIX dan XX. Positivisme lahir bermula dari pemikiran Henry Saint Simon dan Auguste Comte. Positivisme dalam paradigma hukum menyingkirkan pemikiran metafisik yang abstrak. Setiap norma hukum harus diwujudkan ke dalam sebuah norma yang konkrit dan nyata.12 Bahkan, paham positivistik sering menganggap bahwa pemahaman metafisik dan teologis terlalu primitif dan kurang rasional. Artinya kebenaran metafisik dan teologis dianggap ringan dan kurang teruji. Singkat kata, positivistik lebih berusaha mencari fakta atau sebab-sebab terjadinya fenomena secara objektif, terlepas dari pandangan pribadi yang bersifat subjektif. Positivisme turut mempengaruhi bidang hukum ketika mencapai puncaknya pada paruh pertama abad ke-19 M, seiring munculnya berbagai pengaturan dalam bentuk hukum yang menuntut kepatuhan serta memberi ancaman sanksi agar tercipta masyarakat yang teratur. Struktur masyarakat yang semakin kompleks, tingkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta semakin pesatnya perdagangan antarbangsa, membutuhkan para yuris profesional untuk menangani permasalahan hukum. Para yuris yang mendasarkan karyanya pada hukum positivistis-analitis membangun pemikiran rasional dalam memandang hukum sebagai sebuah sistem yang utuh.13 Dampak lain pemikiran aliran positivisme dalam hukum adalah berkembangnya ilmu hukum dengan menggunakan format ilmu sosial dalam paradigma ilmu empiris. Para ilmuwan hukum merasa lebih percaya diri apabila menggunakan pendekatan sosial empiris. Dengan menggunakan pendekatan ini, penjelajahan ilmu hukum akan lebih ilmiah karena dapat dikuantifikasi dan memungkinkan digunakannya rumus-rumus ilmu pasti untuk menjamin pembuktian ilmiah dari segi empiris. Pemikiran Comte menginginkan apa yang bersifat sosial dalam masyarakat dapat diredusir ke dalam dalil-dalil yang pasti sehingga lebih bersifat ilmiah sesuai hukum tiga tahap yang dikembangkannya.14 Secara epistemik-falsafati, positivisme hukum lahir sebagai kritik atas aliran hukum kodrat. Dengan senjata rasio, positivisme hukum menolak aliran hukum kodrat yang terlampau idealistik.15 Istilah positif dalam positivisme hukum merupakan terjemahan dari ius positum menjadi hukum positif yang mengandung makna hukum yang ditetapkan. Jadi, munculnya istilah ius positum pada zaman hukum Romawi jauh lebih awal sebelum pemunculan karya-karya pemikiran Comte. Dalam etimologi Latin, positivisme atau positivus mempunyai makna ditetapkan, ditentukan oleh kehendak, dikehendakkan, dan positif. Makna lain dari positivisme adalah meletakkan, yaitu bahwa tindakan manusia itu adil atau tidak, sepenuhnya bergantung pada peraturan atau hukum yang diletakkan atau diberlakukan.16 Para eksponen positivisme hukum, diantaranya: H.L.A. Hart, J.Austin, dan Hans Kelsen.17 H.L.A. Hart, seorang positivis modern berpengaruh di Inggris, membangun tesis tentang positivisme dengan memisahkan secara tegas keterkaitan antara hukum dan moral. Sikap seperti ini sangat berlawanan dengan pandangan aliran hukum alam yang menegaskan bahwa hukum 11 Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2011), 69-70. 12 Abu Yasid, Aspek-Aspek Penelitian Hukum (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010), 101. 13 Ibid., 88. 14 Moch. Koesnoe, Kritik terhadap Ilmu Hukum (Yogyakarta: Lembaga Riset dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum UII, 1981), 3. 15 Sulistyowati Irianto, dkk, Metode Penelitian Hukum., 8. 16 Abu Yasid, Aspek-Aspek., 117. 17 Khudzaifah Dimyati, Pemikiran Hukum (Yogyakarta: Genta Publishing), 29.
Kitab Al-Risa<lah Dalam Tilikan Positivisme Hukum 5 Kodikasia, Volume, 12 No. 1 Tahun 2018 dan moral tidak dapat dipisahkan. Pengaruh Comte terhadap pemikiran Hart tampak pada waktu ia menguraikan gagasan tentang hukum murni yang terpisah dari aspek moral.18 Di dalam aliran positivisme kepastian hukum merupakan tujuan utama, sedangkan keadilan dan ketertiban menjadi hal yang dinomor dua kan. Diskursus antara kepastian hukum dan keadilan telah lama mengemuka, dengan aliran positivisme tersebut hukum seolah-olah terpisah dari nilai-nilai keadilan yang ada di tengah masyarakat. Untuk itu diperlukan sebuah renovasi baru terhadap hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat tanpa menghilangkan kepastian hukum. Aliran positivisme hukum telah memperkuat ajaran legisme, yaitu suatu ajaran yang menyatakan tidak ada hukum di luar undang-undang, undang-undang menjadi sumber hukum satu-satunya. Undang-undang dan hukum diidentikkan. Dalam positivisme, setiap norma hukum harus eksis dalam alamnya yang obyektif sebagai norma-norma yang positif, serta ditegaskan dalam wujud kesepakatan kontraktual yang konkret antara warga masyarakat atau wakil-wakilnya. Di sini hukum bukan lagi dikonsepsikan sebagai asas-asas moral metayuridis yang abstrak tentang hakikat keadilan, melainkan ius yang telah mengalami positivisasi sebagai lege atau lex, guna menjamin kepastian mengenai apa yang terbilang hukum, dan apa pula yang sekalipun normatif harus dinyatakan sebagai hal-hal yang bukan terbilang hukum.19 Aliran positivis mengklaim bahwa ilmu hukum adalah sekaligus juga ilmu pengetahuan tentang kehidupan dan perilaku warga masyarakat (yang semestinya tertib mengikuti norma- norma kausalitas), maka mereka yang menganut aliran ini mencoba menuliskan kausalitas- kausalitas itu dalam wujudnya sebagai perundang-undangan. Kausalitas dalam kehidupan manusia itu bukanlah kausalitas yang berkeniscayaan tinggi sebagaimana yang bisa diamati dalam realitas-realitas alam kodrat yang mengkaji “prilaku” benda-benda anorganik. Hubungan-hubungan kausalitas itu dihukumkan atau dipositifipkan sebagai norma dan tidak pernah dideskripsikan sebagai nomos, norma hanya bisa bertahan atau dipertahankan sebagai realitas kausalitas manakala ditunjang oleh kekuatan struktural yang dirumuskan dalam bentuk ancaman-ancaman pemberian sanksi.20 Terkait dengan kondisi di Indonesia maka persoalannya tidak bisa terlepas dari kenyataan sejarah dan perkembangan hukum, sehingga dapat dipahami bila saat ini terdapat perbedaan cara pandang terhadap hukum di antara kelompok masyarakat Indonesia. Berbagai ketidakpuasan atas penegakan hukum dan penanganan berbagai persoalan hukum bersumber dari cara pandang yang tidak sama tentang apa yang dimaksud hukum dan apa yang menjadi sumber hukum.21 Para aparat penegak hukum terperangkap kedalam pola pikir postivisme sehingga menganggap hukum sebatas undang-undang. Positivisme hukum adalah bagian yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh perkembangan positivisme (ilmu). Dalam definisinya yang paling tradisional tentang hakikat hukum, dimaknai sebagai norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan. Dari segi ontologinya, pemaknaan tersebut mencerminkan penggabungan antara idealisme dan materialisme. Oleh Bernard Sidharta dikatakan, penjelasan seperti itu mengacu pada teori hukum kehendak (the will theors of law) dari Jhon Austin dan teori hukum murni Hans Kelsen. Berbeda dengan pemikiran hukum kodrat yang sibuk dengan permasalahan validasi hukum buatan manusia, maka pada positivisme hukum, aktivitasnya justru diturunkan kepada permasalahan konkret. 18 Abu Yasid, Aspek-Aspek., 118. 19 Soetandyo Wignjosobroto, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya (Jakarta: Elsam & Huma, 2002), 96. 20 Ibid. 21
6 Abdul Mun’im, Lukman Santoso, Niswatul Hidayati Kodikasia, Volume, 12 No. 1 Tahun 2018 Masalah validitas (legitimasi) aturan tetap diberi perhatian, tetapi standar regulasi yang dijadikan acuannya adalah norma-norma hukum.22 Hart mengemukakan berbagai arti dari positivisme tersebut sebagai berikut: 1. Hukum adalah perintah. 2. Analisis terhadap konsep-konsep hukum berbeda dengan studi sosiologis, historis dan penilaian kritis. 3. Keputusan-keputusan dideduksi secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada lebih dahulu, tanpa perlu merujuk kepada tujuan-tujuan sosial, kebijaksanaan dan moralitas. 4. Penghukuman secara moral tidak dapat ditegakkan dan dipertahankan oleh penalaran rasional, pembuktian atau pengujian. 5. Hukum sebagaimana diundangkan, ditetapkan, positum, harus senantiasa dipisahkan dari hukum yang seharusnya diciptakan, yang diinginkan23. Menurut Thomas Aquino, hukum positif dinamakan Undang-undang Manusia (Menschelijke Wet) adalah hukum yang ada dan berlaku. Menurutnya, undang-undang tersebut tidak didasarkan kepada alam, akan tetapi didasarkan akal. undang-undang tersebut harus mengabdi kepentingan umum karena undang-undang adalah suatu peraturan tertentu dari akal yang bertujuan untuk mengabdi kepentingan umum dan berasal dari satu “kekuasaan” yang sebagai penguasa tertinggi harus memelihara kesejahteraan masyarakat. Hukum positif adalah sesuatu yang perlu untuk umat manusia, hukum positif kebanyakan ditaati oleh manusia dengan sukarela dengan jalan peringatan-peringatan dan tidak oleh karena paksaan oleh undang-undang. Dalam rangka kepentingan menjamin kepastian hukum, positivisme hukum mengistirahatkan filsafat dari kerja spekulasinya, dan mengidentifikasi hukum dengan peraturan perundangan. Melalui tokohnya Hans Kelsen, dengan teorinya hukum murni, positivisme hukum modern berupaya membersihkan ilmu hukum dari anasir-anasir non hukum, seperti sejarah, moral, sosiologis, politis, dan sebagainya. Kelsen hanya ingin menerima hukum apa adanya, yaitu berupa peraturan-peraturan yang dibuat dan diakui oleh negara.24 Sementara, melalui teori Stufenbau Des Rech, yang berasal dari muridnya Adolf Merkl, Kelsen mengintrodusir tentang adanya hierarki perundang-undangan.25 Ajaran Stufenbau theory ini berpendapat bahwa suatu sistem hukum adalah suatu hierarkis dari norma-norma hukum positif, di mana suatu ketentuan hukum tertentu bersumber pada ketentuan hukum lainnya yang lebih tinggi. Sebagai ketentuan yang lebih tinggi adalah Grundnorm atau norma dasar yang bersifat hipotesis. Ketentuan yang lebih rendah adalah lebih konkret daripada ketentuan yang lebih tinggi.26 Sebagai contoh, dapat dilihat dalam ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia. Hakikat Hukum Menurut al-Sha>’i< dalam al-Risa>lah Hukum Islam diturunkan sebagai wahyu dari Allah, tetapi dalam proses transformasinya diperlukan ‘agen’ penyampai untuk menjadi mediator antara sumber sakral dari langit dengan kehidupan manusia. Dalam konteks inilah, Muhammad saw. dipercaya sebagai Nabi untuk menjadi agen penyampai yang mampu membahasan ajaran Islam dalam bahasa masyarakat 22 Anthon F. Susanto, Ilmu Hukum Non Sistemik; Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), 71. 23 Satjipto Raharjo, Buku Materi Pokok Pengantar Ilmu Hukum Bagian IV (Jakarta: Karunika, 1985), 111. 24 Ibid., 273. 25 Munir Fuadi, Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Jakarta: kencana, 2013), 127-130. 26 Ibid., 131-137.
Kitab Al-Risa<lah Dalam Tilikan Positivisme Hukum 7 Kodikasia, Volume, 12 No. 1 Tahun 2018 awam.27 Dalam proses inilah segala kegiatan dan keputusan yang diambil oleh Nabi sebagai wahyu di luar al-Qur’an terejawantahkan, yang dalam definisi umum disebut sebagai sunnah.28 Dari kedua sumber itulah para ahli hukum Islam, termasuk al-Sha>fi’i< mengembangkan sistem hukum yang dalam literatur Islam disebut syari’ah.29 Diambil dari istilah bahasa Arab yang bermakna jalan. Syari’ah merepresentasikan jalan hidup yang telah didesain oleh Allah dan rasul-Nya untuk kehidupan umat Islam.30 Syari’ah didefinisikan sebagai apa yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya baik berupa akidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun aturan- aturan hidup manusia dalam berbagai aspek kehidupannya untuk mengatur hubungan umat manusia dengan Tuhan mereka dan mengatur hubungan mereka dengan sesama mereka serta untuk mewujudkan kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat.31 Di samping itu, syari’ah juga mencakup hukum-hukum Allah bagi tiap-tiap perbuatan manusia, yakni halal, haram, makruh, sunnah, dan mubah. Derivasi dari syariah dalam berbagai konsep hukum teknis dan aplikatif ini kemudian disebut fiqh.32 Menurut al-Sha>fi’i<, hakikat hadirnya hukum adalah dengan diwahyukannya al-Qur’an sumber hukum utama dan tertinggi. Berikutnya dalam hierarki sumber hukum Islam terdapat Sunnah, yang merupakan penjelasan tentang ucapan, perbuatan, dan tingkah laku Nabi (termasuk sikap diam beliau terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu). Sunnah kerap dijadikan aturan untuk persoalan-persoalan yang tidak disebutkan dalam al-Qur’an. Sumber hukum selanjutnya adalah Ijma’, yaitu pendapat-pendapat yang diterima secara umum di kalangan ulama, terutama cendekiawan hukum dalam menafsirkan dua sumber hukum utama tadi.33 Selain itu juga terdapat terdapat sumber hukum yang disebut qiyas, yaitu penalaran dengan logika, terutama terkait persoalan-persoalan kontemporer untuk menghasilkan regulasi untuk situasi yang tidak secara langsung dicakup sumber-sumber dasar.34 Oleh karenanya hukum Islam dipahami al-Sha>fi’i< sebagai institusi yang tidak berakar maupun dicangkokkan pada sosiologi sebagaimana positivisme hukum. Hukum Islam merupakan sarana mengabdi kepada Tuhan, dan bukan kepada masyarakat, meskipun pada aspek teknisnya sangat memahami kondisi masyarakat. Prinsip yang bekerja disini adalah manusialah yang harus menaati hukum dan bukan hukum yang harus diciptakan sesuai dengan keinginan manusia. Oleh karena itu hukum Islam didesain sangat konprehensif dan berlaku sepanjang zaman.35 Ini tentu berbeda dengan positivisme yang dijabarkan Hart melalui bukunya “The Concept of Law,” menurutnya hukum memiliki kelemahan alamiah berupa keterbatasan bahasa serta keterbatasan jangkauannya akan situasi-situasi yang muncul di masa depan. Peraturan seringkali terkendala 27 Ibid., 75-76. 28 Abdul Mun’im Saleh, Otoritas, 42 29 Kata syari’ah dan derivasinya digunakan lima kali dalam al-Qur’an yakni (Surat Al-Syura>, 42 :13, 21. Al- A’raf, (7) :163, Al- Maidah (5) :48, dan Al-Jasiyah (45) :18). 30 Ratno Lukito, Hukum ..., 76. 31 Marzuki, Hukum Islam (Yogyakarta: FIS UNY, 2011). Lihat pula Muhammad Yusuf Musa, Islam; Suatu Kajian Komprehensif (Jakarta: Rajawali, 1988), 131. 32 Kata fikih dalam al-Qur’an digunakan dalam bentuk kerja (fi’il) dan disebut sebanyak 20 kali. Kata fikih bermakna memahami, sebagaimana tercantum dalam Surat Al-An’am ayat 65 yang artinya “Perhatikanlah, betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran, kami silih berganti, agar mereka memahaminya”. Fikih secara etimologis, bermakna paham. Namun berbeda dengan ‘ilm yang artinya mengerti. Ilmu bisa diperoleh secara nalar atau wahyu, fikih menekankan pada penalaran, meski penggunaannya terikat kepada wahyu. Lihat Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006), 3-4. 33 Michael Bogdan, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, terj. Derta Sri Widowatie (Bandung: Nusa Media, 2010), 289-300. 34 Selain sumber hukum yang disepakati, dalam Islam juga dikenal sumber hukum yang tidak disepakati, diantara, Istihsan (kebaikan), ‘Urf (tradisi), Istishab, Maslahah al-Mursalah, Syadd al-Dzara’i, Syar’u man Qablana (Syari’at umat sebelumnya), dan Qaul Shahabi (perkataan sahabat). Lihat “Sumber-Sumber Hukum Islam,” dalam http:// id.wikipedia.org, akses pada 11 Februari 2014. Lihat pula Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 82. 35 Ibid., 79.
8 Abdul Mun’im, Lukman Santoso, Niswatul Hidayati Kodikasia, Volume, 12 No. 1 Tahun 2018 oleh masalah bahasa yang kurang lugas dan menimbulkan beragam interpretasi (multi tafsir). Demikian juga peraturan seringkali tidak dapat mengantisipasi situasi-situasi yang muncul kemudian, sehingga diperlukan ruang diskresi bagi hakim untuk mencocokan peristiwa hukum dengan peraturan yang mengaturnya.36 Ide hukum sebagai entitas yang mencakup segalanya menjadi karakter utama bagaimana Islam memandang kehidupan ini.37 Termasuk persoalan hubungan dengan Tuhan (ḥabl min Alla>h), hubungan sesama manusia (ḥabl min an-na>s), termasuk refleksi hubungan manusia dengan Tuhan.38 Konsep inilah yang sulit dipahami oleh sebagian besar orang Barat. Dengan kondisi demikian, Hukum Islam yang disajikan dalam al-Risa>lah adalah hukum yang berkarakter, Ia mempunyai ciri-ciri khas. Beberapa karakter yang umum misalnya, takamul (utuh), kamīl (sempurna), universal, dinamis, sistematis, humanis, dll. Berbagai karakter itulah yang kemudian membentuk Islam dalam sebuah sistem hukum yang komprehensif dengan titik tekan pada implementasi nilai dan moral agama, karena untuk membentuk suatu interaksi sosial kemanusiaan dalam sebuah sistem hukum negara, tentu manusia harus memiliki aspek moral (akhlak) yang baik. Tentu ini berbeda dengan paham positivisme yang menghendaki dilepaskannya pemikiran metayuridis mengenai hukum sebagaimana dianut oleh para pendukung aliran hukum alam (naturalis) atau aliran hukum kodrat. Karena itu menurut paham positivisme, setiap norma hukum harus eksis dalam alamnya yang objektif sebagai norma-norma yang positif, serta ditegaskan dalam wujud kesepakatan kontrak yang konkret antar warga masyarakat atau wakil-wakilnya. Dalam konteks ini, hukum bukan lagi dikonsepsikan sebagai asas-asas moral metayuridis yang abstrak tentang hakikat keadilan atau bernilai moral, melainkan sesuatu yang telah mengalami positivisasi guna menjamin kepastian mengenai apa yang terbilang hukum.39 Sehingga, dalam positivisme, tindakan manusia itu adil atau tidak, patut atau tidak sepenuhnya bergantung pada peraturan atau hukum yang diletakkan atau diberlakukan. Dalam perspektif al-Risa>lah , apa yang disoroti kaum positivis terkait hukum yang irasional sebenarnya mengarah pada elemen hukum ibadah (ritual) yang memang mempunyai watak immutable dan tidak didasarkan pada fakta empiris dan logis. Dalam ranah hukum ibadah unsur akal-budi dan intelektual manusia tidak banyak berperan dalam proses penelusuran makna di balik apa yang tersurat. Sebaliknya, dalam elemen hukum mu’amalah penilaian Comte, Austin dan Kelsen bahwa hukum merupakan bagian dari metafisika yang tidak masuk akal dan tidak memuat unsur moral tidak memiliki relevansinya. Sebab, muatan hukum mu’amalah dalam Islam selain sangat positivistik juga mengapresiasi nilai-nilai moral dalam membangun pranata sosial berbasiskan ketentuan-ketentuan hukum operasional. Hal ini tentu bertolak belakang dengan positivisme yang justru memisahkan hukum dengan moral. Selain itu, akal-budi manusia mempunyai peran cukup signifikan dalam rangkaian kerja istinbath untuk menelorkan ketentuan-ketentuan hukum. Sumber inspirasi dalam hukum mu’amalah selain berupa prinsip- prinsip umum dalam ketentuan wahyu, juga berupa realitas masyarakat dengan aspek perubahan dan pengembangannya yang tidak bisa dielakkan. Hukum Islam, sebagaimana diuraikan dalam al-Risa>lah menempatkan sistem ketuhanan untuk menuntun umat manusia menuju kedamaian di dunia dan di akhirat. Urusan dunia ini oleh penentu hukum dipandang dari kerangka kepentingan dunia lain, yang lebih baik dan abadi. Sehingga hukum perlu dipahami dan terimplementasi secara benar sesuai makna hakiki 36 H. L. A Hart, Konsep Hukum (The Concept of Law), terj. M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 2013), 192- 210. 37 Ratno Lukito, Hukum..., 76. 38 Ibid., 77. 39 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, editor Ifdhal Kasim et.al. (Jakarta: Elsa Elsam & Huma, 2002), 96.
Kitab Al-Risa<lah Dalam Tilikan Positivisme Hukum 9 Kodikasia, Volume, 12 No. 1 Tahun 2018 dari hukum dalam kitab Suci. Hal ini membuktikan perbedaan antara hukum Islam dari hukum yang dibuat manusia yang hanya membicarakan kepentingan dunia belaka. Tuhan adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sifat ini benar-benar terefleksikan dalam setiap hukum- hukum-Nya. Jadi, rahmat merupakan inti syari’ah dengan konsekuensi bahwa kekuasaan yang berdasarkan pada kekuatan akal semata dicela oleh Tuhan. Mengatur dengan kekuatan akal bukan tujuan syari’ah, sedangkan keadilan merupakan tujuan utama. Keadilan menurut hukum Islam adalah perintah yang lebih tinggi, karena tidak hanya memberikan kepada setiap orang akan haknya, tetapi juga sebagai rahmat dan kesembuhan qalbu. Berlaku adil dianggap sebagai langkah taqwa setelah beriman kepada Allah. Oleh sebab itu, hukum Islam merupakan pernyataan Tuhan, dan usaha untuk menegakkan perdamaian di muka bumi dengan mengatur masyarakat dan memberikan keadilan kepada setiap orang. Jadi, perintah dan keadilan merupakan tujuan mendasar bagi hukum Islam (Syari’ah). Pada dimensi hakikat hukum sebagai perintah ini selaras dengan positivisme, sementara pada dimensi hakikat keadilan justru bertolak belakang dengan positivisme. Keadilan dalam Islam merupakan perpaduan harmonis antara hukum dengan moralitas, Islam tidak bertujuan menghancurkan kebebasan individu, tetapi mengontrol kebebasan itu demi keselarasan dan harmonisasi masyarakat, yang terdiri dari individu itu sendiri. Hukum Islam memiliki peran dalam mendamaikan pribadi dengan kepentingan kolektif, bukan sebaliknya. Individu diberi hak untuk mengembangkan hak pribadinya dengan syarat tidak mengganggu kepentingan orang lain. Singkatnya, hukum Islam yang diuraikan al-Risa>lah adalah norma hukum dan norma moral sekaligus.40 Artinya, secara sederhana dapat ditarik benang merah bahwa positivisme dalam definisinya yang paling tradisonal tentang hakikat hukum, dimaknai sebagai norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan yang konkret. Ini tentu berbeda dengan pemikiran hukum Islam yang justru merupakan perwujudan dari norma-norma moral agama. Sumber -sumber Hukum Menurut al-Sha>’i< di dalam al-Risa>lah, dan Hirarkinya serta Bangunan Metodologi Menemukan Hukum Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam, ijitihad dan us}u>l al-fiqh merupakan dua istilah yang memiliki hubungan erat. Kedua Istilah tersebut juga erat kaitannya dengan bagaimana teks dapat menjadi produk fiqh di tengah-tengah masyarakat. Serta bagaimana teks wahyu dapat membumi dalam perilaku masyarakat. Pemikir Islam kontemporer, Ali Harb, mengatakan bahwa teks memiliki gagasan dan dunianya sendiri. Kebenaran bukanlah esensi yang melampaui kondisinya, atau ditemukan terpisah dari wacananya, melainkan ia diciptakan oleh teks itu sendiri.41 Hal inilah yang oleh al-Sha>fi’i< melalui karyanya Al-Risa>lah mencoba untuk dimaknai secara jernih dengan mengunakan penalaran bercorak teologis deduktif, sebuah persoalan tidak eksplisit ditemukan hukumnya dalam al-Qur’an dan sunnah. Al-Sha>fi’i< membangun teori hierarki hukum Islam didasarkan pada empat sumber yaitu, al-Qur’an, sunnah Nabi, konsensus ulama (ijmak), dan metode analogi (qiyas).42 Pokok-pokok teori sumber hukum Islam ini dibangun oleh al-Sha>fi’i< . Jika ditilik dari perspektif positivisme hukum, maka teori sumber hukum Islam yang dibangun oleh al-Sha>fi’i< kurang lebih sama dengan teori tingkatan norma Hans Kelsen. Dimana menurut al-Sha>fi’i< , dalam menjawab berbagai persoalan hukum yang dihadapi oleh orang-orang Muslim 40 Muhamad Erwin, Filsafat Hukum, 295. 41 Lukman Santoso, “Nomenklatur Pemikiran,” 84. 42 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh (t.tp: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th), 17.
10 Abdul Mun’im, Lukman Santoso, Niswatul Hidayati Kodikasia, Volume, 12 No. 1 Tahun 2018 dipecahkan dengan bantuan sumber-sumber hukum Islam tersebut secara bertingkat atau berurutan.43 Ditinjau dari aspek metodologi, hukum Islam merupakan hasil ijtihad, maka hukum Islam tidak memiliki sifat kebenaran yang absolut.44 al-Sha>fi’i< mencurahkan sebagian besar tulisan- tulisannya untuk berdiskusi dengan dan berpolemik melawan penentang-penentangnya, namun selalu dengan maksud agar mereka mengakui dan mengikuti sunnah Nabi, dan dia berulangkali menentang taklid buta terhadap pendapat seseorang.45 Perkembangan lain yang berkaitan dengan formalisasi hukum Islam oleh al-Sha>fi’i< adalah terbentuknya kaidah-kaidah hukum yang sebagian besar telah berubah menjadi hadis-hadis dari Nabi. Meskipun tidak semua kaidah-kaidah hukum itu berhasil berubah menjadi hadis dengan isnad yang dapat diterima. Misalnya, pada kaidah “barangsiapa yang bekerjasama dengan suatu kaum maka ia adalah bagian dari kaum itu” yang digunakan sebagai sebuah argumen oleh Awza’i. Penalaran lain tentang kaidah ini adalah penalaran Irak kuno terkait kedudukan budak dalam hukum waris dengan bunyi kaidahnya yang dinisbatkan kepada Ibn Mas’ud “seorang budak itu terhalangi dan tidak dapat mewariskan”. Bentuk ini memperlihatkan satu jenis penalaran kuno seolah-olah hak mewarisi merupakan suatu kuasa yang diberikan dari seseorang melalui orang lain kepada orang ketiga. Kemudian Sha>fi’i< mengembangkan sebuah penalaran hukum yang bersifat teknis dan ketat yang mereka nyatakan dalam kaidah “budak tidak dapat mewarisi dan tidak mewariskan” (al-‘abd la yaris wa-la yuris). Kaidah ini diambil dari kaidah pertama (dengan perubahan makna dalam kata yuris) dan menunjukkan bahwa budak tidak menghalangi siapa pun dari menerima warisan. Secara keseluruhan, teori hirarkhi sumber hukum al-Sha>fi’i< ini merupakan satu sistem sumber hukum yang konsisten dan jauh lebih unggul dibandingkan dengan doktrin mazhab-mazhab kuno. Keberhasilan al-Sha>fi’i< merupakan hasil logis dari sebuah proses yang berawal ketika hadis-hadis Nabi pertama kali dikemukakan sebagai argumen-argumen hukum. Perkembangan teori hukum didominasi oleh pertarungan antara dua konsep, yakni konsep doktrin yang umum di masyarakat, dan konsep otoritas hadis dari Nabi. Jika dibandingkan dengan positivisme, yang memiliki ciri bahwa hukum itu dibuat dalam bentuk tertulis, dan hakim terikat dengan peraturan-peraturan tertulis, hierarki sistem hukum Islam juga terkodifikasi dalam bentuk tertulis, yakni al-Qur’an dan Sunnah. Meskipun bentuk tertulisnya merupakan bagian dari ijtihad, hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki persamaan. Disamping itu juga sumber hukum Islam memiliki dimensi berbeda. Sumber hukum Islam dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu dalil naལ (yuridis) dan ghairu na>sh (metayuridis). Sumber nash (yuridis) yaitu al-Qur’an dan As–sunnah, sedangkan sumber ghairu na>ལ (metayuridis) berupa qiyas, dan sebagainya. Artinya, dalam hukum Islam, hasil ijtihad itu kemudian dijadikan sumber untuk tersusunnya aturan atau undang-undang (rules) dan dalam waktu bersamaan juga berupa ketentuan prinsip (di dalamnya termasuk qawa>’idul fiqhiyyah) yang dijadikan landasan para hakim (qaལi) untuk membuat suatu keputusan terhadap kasus-kasus di pengadilan. Sumber utama yakni wahyu dan ijtihad inilah yang merupakan perbedaan mendasar antara hukum Islam dengan sistem hukum positif.46 Artinya, dalam hukum positif, menggunakan kodifikasi hukum tertulis buatan manusia sebagai sumber hukum, sedangkan sistem hukum Islam sumber hukum utama yaitu, al-Qur’an, Sunnah, meskipun terkodifikasi tetapi bersumber dari wahyu. 43 Ahmad Minhaji, Kontroversi Pembentukan Hukum Islam; Kontribusi Joseph Schacht, terj. Ali Mahrus (Yogyakarta: UII Press, 2001), 24. 44 Ngainun Naim, Sejarah Pemikiran Hukum Islam; Sebuah Pengantar (Yogyakarta: Teras, 2009), 134. 45 Joseph Schacht, the Origins of Muhammadan Jurisprudence; tentang asal-usul Hukum Islam dan Masalah Otentisitas Sunah, alih bahasa Joko Supomo (Yogyakarta: Insan Madani, 2010), 11-12. 46 Abdul Ghofur Ansori, Hukum Islam..., hlm. 39.
Kitab Al-Risa<lah Dalam Tilikan Positivisme Hukum 11 Kodikasia, Volume, 12 No. 1 Tahun 2018 Sumber positivisme hukum yang terbagi dalam hukum material dan formal juga memiliki aspek perbedaan dengan hukum Islam. Sumber hukum material merupakan materi-materi hukum berupa perilaku dan realitas yang ada di masyarakat. Sedangkan sumber hukum formil adalah 1) Undang-undang, 2) Kebiasaan, 3) Yurisprudensi, 4) Traktat, dan 5) Doktrin. Sementara Hukum Islam juga mempunyai sumber hukum material, namun memiliki substansi berbeda dengan positivisme, yaitu bahwa sumber hukum Islam berasal dari wahyu, sedangkan hukum positif bersumber kepada perilaku dan realitas dalam masyarakat. Adapun Urf sebagai kebiasaan yang dapat disebut juga perilaku masyarakat, masih harus dipilah menjadi ‘urf ལahih (yang sesuai dengan nash atau sumber hukum tekstual) dan ‘urf baལil (yang tidak sesuai dengan nash), sehingga yang dapat dijadikan sumber hukum hanyalah ‘urf ལahih.47 Eksistensi hukum pada prinsipnya merupakan tatanan sistem nilai. Dalam konteks eksistensi positivisme hukum ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia selaku anggota masyarakat (odening van het sociale leven) agar tercipta kepastian hukum. Artinya adanya masyarakat adalah yang menjadikannya adanya hukum (ubi societas ibi ius) sehingga hukum itu ada (raison d’etre) karena adanya conflicts of human interest. Tentu eksistensi ini berbeda dalam sistem hukum Islam, hukum hadir dalam Islam untuk mengatur kehidupan manusia, baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat agar dapat bertingkah laku yang sesuai dengan kehendak Sang pencipta. Dari hal ini terlihat bahwa konsepsi positivisme hukum cenderung melihat hukum karena adanya interaksi antar manusia, adapun aturan yang hanya berkaitan dengan kehidupan pribadi tidak dinamakan hukum tetapi disebut norma.48 Pada aspek lain, dalam mendefinisikan makna hukum dalam kaitannya dengan agama pun sangat berbeda antara positivisme dan hukum dalam al-Risa>lah. Sebut saja misalnya pendapat al-Sha>fi’i< yang mendudukkan hukum harus dicocokkan dengan ketentuan agama karena hukum berhubungan dengan wahyu secara langsung, sehingga hukum dipandang sebagai bagian dari wahyu. Pendapat berbeda terkait hukum diberikan Austin, yang bermazhab positivisme, menurutnya hukum Tuhan dan hukum manusia itu terpisah, seperti halnya terpisahnya moral dengan hukum.49 Dalam Islam, tidak ada perbedaan antara hukum alam dengan hukum Tuhan (syari’at), karena syariat yang ditetapkan Allah dalam al-Qur’an sesuai dengan hukum alam itu sendiri, yang dalam Islam disebut fitrah. Namun pemaknaan fitrah dalam Islam jauh lebih tinggi daripada pemaknaan alam sebagaimana dipahami dalam konteks positivisme. Jika alam (lex naturale) dipahami sebagai segala yang ada berjalan sesuai dengan aturan semesta alam, seperti manusia dalam bertindak mengikuti kecenderungan-kecenderungan dalam jasmaninya, maka fitrah berarti pembebasan manusia dari keterjajahan terhadap kemauan jasmaninya yang serba tidak terbatas pada kemauan ruhani yang mendekat pada Tuhan. Sikap al-Sha>’i< di dalam al-Risa>lah Terhadap Hal-hal yang Bersifat Non-hukum (Metayuridis) Mayoritas ulama Sunni, bersepakat bahwa us}u>l al-fiqh sebagai disiplin ilmu yang mandiri baru lahir pada awal abad III H, yaitu setelah penyusunan kitab al-Risa>lah, oleh al-Sha>fi’i< (150- 204 H). Sebelum kemunculan al-Sha>fi’i<, ada satu periode terjadinya pertentangan antara rasionalis Kufah dan tradisionalis Basrah. Kufah merupakan pusat pertemuan budaya antar bangsa, terutama masyarakat Persia, jauh dari pusat tradisi Nabi, yaitu Madinah, maka sangat jarang mereka menemukan hadis sehingga banyak menerapkan dalil-dalil rasio seperti qiyas dan istihsan. 47 Abdul Ghofur Ansori, Hukum Islam.... 40-41. 48 Abdul Ghofur Ansori, Hukum Islam..., 31. 49 Abdul Gofur Ansori, Filsafat Hukum, Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2006), 18.
12 Abdul Mun’im, Lukman Santoso, Niswatul Hidayati Kodikasia, Volume, 12 No. 1 Tahun 2018 Al-Sha>fi’i< ingin mencoba mengkompromikan antar kedua wacana tersebut melalui kunjungannya ke daerah-daerah, seperti di Kufah yang diwarnai dengan dialog dengan murid-murid Abu Hanifah, seperti Abu Yusuf dan Imam Muhammad asy-Syaibani, di Yaman menemukan fikih sahabat Mu’az Ibn Jabal, Matraf Ibn Mazin, Hasyim Ibn Yusuf. Ia juga sempat bertemu dengan fikihnya al-Auza’i lewat muridnya ‘Amr Ibn Salamah, dan fikihnya al-Lais lewat muridnya Yahya Ibn Hasan. Bentuk kompromi itu kemudian dirumuskan dalam bentuk sintesis baru, yaitu ushul al-Sha>fi’i< yang dibukukan dalam karyanya yaitu al-Risa>lah, yang nama sebelumnya adalah al-Kitab. Meskipun al-Sha>fi’i< dalam kasanah Islam dikenal sebagai pengkompromi antara dua kubu tradisionalis dan rasionalis, namun menurut Nasr Hamid Abu Zaid, Sha>fi’i< dianggap masih banyak memihak kubu tradisionalis dengan warna fanatisme-rasial Arabnya.50 Dengan lahirnya al-Risa>lah, prestasi yang patut dicatat dalam diri al-Sha>fi’i< antara lain karena 1) Sebagai perintis dasar-dasar konseptual tentang hadits, dan 2) Sebagai peletak utama dasar metodologi hukum Islam. Gejala-gejala itu mulai tampak ketika al-Sha>fi’i< banyak belajar dan berguru tentang hadits kepada Imam Malik. Sejak itulah al-Sha>fi’i< mulai berani memberi perumusan sistematik dan tegas, bahwa sunnah yang harus diikuti bukanlah setiap bentuk sunnah, melainkan sunnah yang hanya berasal langsung dari Nabi. Konsekuensi pemahaman seperti ini ialah bahwa kritik terhadap sunnah dalam bentuknya sebagai laporan dan cerita tentang generasi terdahulu harus dilakukan. Dengan melakukan seleksi ketat, al-Sha>fi’i< kemudian membuat klasifikasi mana yang benar-benar berasal dari Nabi dan mana yang diklaim sebagai dari Nabi. Sejak itu pula semua laporan dan cerita tentang hadits sebagai sumber hukum kedua harus diuji secara teliti menurut standart ilmiah tertentu sebagai diuraikan dalam al-Risa>lah. Kenyataan inilah yang menjadikan al-Sha>fi’i< dijuluki sebagai perintis metodologi hukum Islam tersebut. Penelitian ilmiah terhadap laporan dan cerita Nabi, yang ia rintis telah memperoleh bentuknya yang paling kuat setelah munculnya sarjana hadits kelahiran Bukhara di kawasan Transoksania, yang dianggap paling tinggi otoritas ilmiahnya, yaitu al-Bukhari. Berkat kepeloporan al-Sha>fi’i<, muncul pula secara berturut-turut beberapa tokoh hadits yang kritis, yang secara kolektif karya-karya mereka dinamai dengan al-kutub al-sitah. Banyak hal yang melatarbelakangi as- Shafi’i bertindak kritis seperti ini, antara lain kegiatan pemikiran yang berkembang dengan pesatnya ketika itu, hingga membuka kemungkinan untuk membawa ide-ide dasar agama menjadi relevan dengan perkembangan tuntutan masyarakat, disatu sisi. Meskipun di sisi lain kemampuan intelektual pada ujung-ujungnya juga bermasalah, yaitu pemikiran yang keluar dari teks selalu dianggap sebagai pendapat pribadi/al-ra’y. Sehingga selalu rawan terhadap ancaman subjektivisme. Keadaan inilah yang mendorong al-Sha>fi’i< untuk membuat penajaman batasan dan pemastian keabsahan antara sunnah dan atsar sebagai sumber hukum. Disadari atau tidak metodologi pemikiran hukum Shafi’i ini, ternyata menjadi model yang paling khas di antara beberapa model yang digunakan untuk mendekati dan menggali suatu hukum. Sisi lain yang tidak kalah menarik adalah, bahwa metodologi pemikiran hukum al-Sha>fi’i< sejak diterbitkannya al-Risa>lah hingga kini belum ada tandingannya. Disinilah urgensitas sebuah metodologi yang memiliki daya aktualitas sepanjang sejarah, suatu metodologi yang langsung mengadopsi logika al-Quran. Daya aktualitas dan universalitas metodologi pemikiran hukum Imam Sha>fi’i< tersebut, disatu sisi memudahkan para ulama yang datang kemudian, namun di sisi lain membuat para ulama modern enggan memaksimalkan pemikirannya, dan yang terjadi adalah pengulangan ide-ide lama. 50 Abdul Mughits, Kritik Nalar Fikih Pesantren, (Jakarta: Kencana, 2008), 55.
Kitab Al-Risa<lah Dalam Tilikan Positivisme Hukum 13 Kodikasia, Volume, 12 No. 1 Tahun 2018 Karena kepeloporan al-Risa>lah banyak juga pemikir muslim yang juga mensarah kitab ini, diantaranya Syarh Abi Bakr al-Shairafi (w.330 H), dan Syarh Abu al-Walid al-Naisaburi Muhammad Ibn Abdillah (w. 388 H). Edisi yang saat beredar adalah edisi yang dicetak Mathba’ah Mesir 1358 H.51 Dengan demikian setiap ulama yang akan menetapkan suatu hukum atas suatu kejadian/ fenomena, tentu mereka akan lebih dahulu menetapkan metode berpikir mana yang akan dipilih dan diikuti. Dan bukan metodolgi yang dikreasi sendiri, yang selalu memiliki relevansi dan signifikansi terhadap tuntutan budayanya. Meskipun dari berbagai sisi diketahui bahwa metode berpikir akan sangat menentukan hasil keputusan akhir dari suatu hukum. Indikasi ini bisa dilihat dari ragamnya para ulama fiqh dalam memilih dan menerapkan metode berpikirnya, hingga berakhir pada formulasi fiqh yang berbeda pula. Sayangnya tidak banyak ulama kontemporer yang mampu memfungsikan orisinalitas pemikirannya untuk melakukan istinbath hukum. Karena mayoritas di antara mereka masih banyak yang merujuk metodologi Imam madzhab yang dipandang memiliki otoritas keagamaan yang memadai. Sementara metodologi Imam madzhab dibuat sesuai dengan situasi dan kondisi sosio kultural ketika itu. Tentu metodologi pemikiran sepertinya kurang relevan dengan perkembangan budaya kekinian. Padahal upaya para ahli fiqh dalam menggali hukum Islam dari sumber-sumbernya tidak akan membuahkan hasil yang memadai, bila menggunakan cara-cara yang kurang tepat. Dalam pandangan Ali Hasbullah, ada dua cara pendekatan yang dikembangkan oleh para ulama ushul fiqh dalam melakukan istinbath hukum, yaitu a). melalui pendekatan kaidah-kaidah kebahasaan (teks) dan b). dengan pendekatan makna atau maksud syari’ah (konteks). Cara- cara pendekatan seperti ini, dari satu aspek memiliki kekurangan karena pendekatan sepertinya masih bersifat umum. Dan metodologi model apapun, selama masih bersinggungan dengan teks bahasa (al-Qur’an dan al-Hadits), tidak akan bisa lepas dari trend seperti di atas. Dengan kata lain trend metodologi di atas bukanlah trend yang baru, tetapi trend yang sudah wajar, di mana sejak orang Islam berkeinginan menggali hukum juga melewati model seperti ini. Berbeda dengan metodologi pemikiran hukum al-Sha>fi’i< yang muncul beberapa abad yang lalu. Sebuah metodologi yang telah mengenalkan kaidah-kaidah teoritik yang diilhami oleh logika al-Quran. Tentu metodologi sepertinya adalah metodologi yang telah melalui proses panjang, antara lain pertanyaan al-Sha>fi’i< menyangkut esensi al-Quran. Apakah ia hanya makna semata atau makna yang dibungkus dengan kata-kata. Bagi al-Sha>fi’i< suatu pendekatan yang jarang dilakukan adalah pendekatan yang terinci menyangkut penggunaan dalil dan pemaknaan atas dalil. Jika para ulama berbeda dalam wilayah penggunaan dalil berikut berbeda atas pemahaman dalil tersebut, maka formulasi fiqhnya pun juga akan jauh berbeda. Baginya dua pokok pemikiran ini merupakan persoalan yang fundamental. Istilah dalil yang digunakan al-Sha>fi’i< di atas agaknya identik dengan sumber hukum. Kata sumber untuk hukum Islam ini, merupakan terjemahan dari Arab, yaitu mashadir, dimana kata tersebut hanya digunakan oleh sebagian kecil para penulis kontemporer dalam hukum Islam, sebagai ganti dari sebutan al- ‘Adillah al-Syari’iyah dan tidak ditemukan adanya istilah mashadiru al-ahkam. Ini artinya kedua terma di atas secara umum, memiliki makna konteks yang sama (dekat). Dengan demikian bisa dikatakan bahwa pengguanaan dalil dan pemaknaan dalil sama artinya dengan penggunaan sumber hukum dan pemaknaan atas sumber hukum. Disinilah para ulama banyak menemukan perbedaan-perbedaan, mulai dari pembatasan sumber yang sah untuk digunakan dalil dan yang tidak sah untuk digunakan dalil. Lebih-lebih menyangkut pemaknaan atas dalil atau sumber hukum tersebut. 51 Satria Efendi M. Zein, Ushul Fiqh, 26
14 Abdul Mun’im, Lukman Santoso, Niswatul Hidayati Kodikasia, Volume, 12 No. 1 Tahun 2018 Itulah sebabnya al-Sha>fi’i< segera menaruh perhatian yang besar untuk menyusun metodologi pemikiran hukum (ushul fiqh), hingga muncullah karya monumentalnya yang berjudul al- Risa>lah. Sejak itu pula murid-murid dan pengikut madzhabnya di kemudian hari tetap merujuk kepada kitab al-Risa>lah tersebut. Pembicaraan menyangkut dalil-dalil syara’, al-Sha>fi’i< membagi istilah dalil menjadi dua, yaitu dalil yang sah yang wajib diamalkan dan dalil yang sah, tetapi sebenarnya tidak sah. Yang dimaksud dalil yang sah menurut al-Sha>fi’i< dan memiliki kekuatan hukum adalah al-Quran, Sunnah, Ijma’, Qiyas dan Istishhab. Sedangkan yang lainnya merupakan dalil yang dikelompokkan pada dalil yang diperselisihkan, yaitu istihsan, maslahah mursalah, ‘urf, madzhab shahabi, syar’u man qablana, adalah termasuk dalil-dalil yang tidak sah dan tidak wajib diamalkan menurut al- Shafi’i. Posisi al-Sha’i< dalam al-Risa>lah Terhadap Tujuan Hukum Berbeda dengan positivisme yang hanya berpijak pada fakta empiris. Sehingga tujuan dengan adanya hukum hanyalah bersifat aspek kepastian. Hukum Islam justru bertolak pada wahyu, yang mengidealkan hukum sebagai pranata keadilan yang muaranya adalah untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah sebagaimana yang tertera dalam rumusan maqasid as-syari’ah, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan dan harta.Tujuan hukum Islam di atas dapat dilihat dari dua sudut yaitu dari sudut pembuat hukum Islam (Allah SWT. dan Rasullah) dan sudut manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam tersebut.52 Stabilitas hubungan dalam masyarakat menurut positivisme dapat dicapai dengan adanya peraturan hukum yang bersifat mengatur (anvullenrecht) dan aturan-aturan hukum yang bersifat memaksa (dwingenrecht) setiap anggota masyarakat agar taat dan mematuhi hukum. Secara garis besar, hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Sehingga dari sini, dapat diketahui bahwa tujuan positivisme hukum hanya dalam wilayah kehidupan dunia. Sedangkan dalam hukum Islam bertujuan untuk kebahagiaan hidup manusia di semua aspek, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan menolak yang madharat. Mengkaji dan mendalami hukum Islam berbeda dengan cara penetapan hokum lainnya. Hukum Islam tidak boleh dikaji akal dengan sebebas-bebasnya, akan tetapi harus mengikuti kaidah hukum syara’ yang terikat dengan landasan hukum Islam. Oleh karena itu, seorang mujtahid memerlukan kerangka teori atau metodologi berpikir dalam menggali fikih yang disebut dengan ushul fikih.53 Sementara prosesnya dipahami sebagai ijtihad, yakni proses metodologis dalam memahami hukum yang bersumber dari al-Quran dan sunnah. Karakteristik hukum Islam yang bersendikan nash dan didukung dengan akal merupakan ciri khas yang membedakan hukum Islam dengan sistem hukum lainnya. Ijtihad memegang peranan signifikan dalam pembaruan hukum Islam.54 Ijtihad sebagai sebagai suatu prinsip dan gerak dinamis dalam khazanah Islam merupakan aktivitas daya nalar yang dilakukan oleh para ahli hukum Islam dalam menggali hukum dan kegiatan ijtihad ini telah mengalami dinamisasi yang panjang. Konsep metodologi hukum yang ditawarkan al-Sha>fi’i< berupaya mengendalikan rasionalitas yang berlebihan yang menghendaki perubahan dan tekstualitas yang berlebihan yang menghendaki kepastian menuju posisi moderat, sebagaimana tertulis dalam kitab Al-Risa>lah . Ia kemudian dikenal sebagai salah satu tokoh Equilibium “keseimbangan” dalam Islam yang menempatkan akal dan wahyu dalam posisi yang seimbang. 52 Moh. Makmun, “Perbandingan Hukum Barat dan Hukum Islam,” AL-HUKAMA, Volume 03, Nomor 02, (Desember 2013), 195. 53 M. Kholil Nafis, Teori Hukum..., 27. 54 Abd. Salam Arief, Pembaruan Pemikiran..., 15.
Kitab Al-Risa<lah Dalam Tilikan Positivisme Hukum 15 Kodikasia, Volume, 12 No. 1 Tahun 2018 Pada dasarnya posisi keseimbangan ini di dapatkan dari gaya legislasi “perundang-undangan hukum” dari Al-qur’an. Pemikiran Hukum Islam sekarang mengambil posisi berikut, yakni mengikuti mengikuti wahyu apa adanya jika, wahyu itu tegas dalam menyampaikan maksudnya “qoth’i”, tetapi melakukan penafsiran jika wahyu memang memberikan kesempatan untuk menafsirkan “dhonni”. Teks wahyu yang qoth’i berguna untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan hukum, universalitas hukum, dan kemampuan hukum. Sedangkan teks wahyu yang dhonni yang bertugas untuk menerima perubahan, keseimbangan, partikulasi, dan pembaharuan hukum. Artinya, diantara bentangan ketentuan ketuhanan yang asli dan pengaturan manusia yang banyak kemungkinannya itu, terhamparlah lapangan yang luas bagi kegiatan dan keputusan intelektual. N.J Coulson melihat peranan dua pihak itu sebagai konflik. Sekalipun Allah sebagai al-Hakim (sang pembuat hukum), dimana Dia, dan hanya Dia, sebagai sumber nilai bagi segala perbuatan subyek hukum, tetapi dalam keyataannya ada ruang gerak bagi keputusan intelektual. Inilah keunikan teknik legislasi al-Qur’an.55 PENUTUP Dari keseluruhan uraian diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, Menurut al- Sha>fi’i<, hakikat hadirnya hukum adalah kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Hukum Islam dipahami al-Sha>fi’i< sebagai institusi yang tidak berakar maupun dicangkokkan pada sosiologi sebagaimana positivisme hukum. Hukum Islam merupakan sarana mengabdi kepada Tuhan, dan bukan kepada masyarakat, meskipun pada aspek teknisnya sangat memahami kondisi masyarakat. Prinsip yang bekerja disini adalah manusialah yang harus menaati hukum dan bukan hukum yang harus diciptakan sesuai dengan keinginan manusia. Oleh karena itu hukum Islam didesain sangat konprehensif dan berlaku sepanjang zaman. Artinya, secara sederhana dapat ditarik benang merah bahwa positivisme dalam definisinya yang paling tradisonal tentang hakikat hukum, dimaknai sebagai norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan yang konkret. Ini tentu berbeda dengan pemikiran hukum Islam yang justru merupakan perwujudan dari norma-norma moral agama. Kedua, Al-Sha>fi’i< membangun teori hierarki hukum Islam didasarkan pada empat sumber yaitu, al-Qur’an, sunnah Nabi, konsensus ulama (ijma’), dan metode analogi (qiyas). Jika ditilik secara konseptual dari perspektif positivisme hukum, maka teori sumber hukum Islam yang dibangun oleh al-Sha>fi’i< kurang lebih sama dengan teori tingkatan norma Hans Kelsen. Dimana menurut al-Sha>fi’i<, dalam menjawab berbagai persoalan hukum yang dihadapi oleh orang-orang Muslim dipecahkan dengan bantuan sumber-sumber hukum Islam tersebut secara bertingkat atau berurutan. Sementara dalam konteks metodologi, hukum Islam merupakan hasil ijtihad, maka hukum Islam tidak memiliki sifat kebenaran yang absolut. al-Sha>fi’i mencurahkan sebagian besar tulisan-tulisannya untuk berdiskusi dengan dan berpolemik melawan penentang- penentangnya, namun selalu dengan maksud agar mereka mengakui dan mengikuti sunnah Nabi, dan dia berulangkali menentang taklid buta terhadap pendapat seseorang. Ketiga, Dalam konteks eksistensi positivisme hukum ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia selaku anggota masyarakat (odening van het sociale leven) agar tercipta kepastian hukum. Artinya adanya masyarakat adalah yang menjadikannya adanya hukum (ubi societas ibi ius) sehingga hukum itu ada (raison d’etre) karena adanya conflicts of human interest. Tentu eksistensi ini berbeda dalam sistem hukum Islam, hukum hadir dalam Islam untuk mengatur kehidupan manusia, baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat agar dapat bertingkah laku yang sesuai dengan kehendak Sang pencipta. Dari hal ini terlihat bahwa konsepsi positivisme 55 Abdul Mun’in Saleh, Madhhab Sha>fi’i<; Kajian Konsep Maslahah (Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001), 41.
16 Abdul Mun’im, Lukman Santoso, Niswatul Hidayati Kodikasia, Volume, 12 No. 1 Tahun 2018 hukum cenderung melihat hukum karena adanya interaksi antar manusia, adapun aturan yang hanya berkaitan dengan kehidupan pribadi tidak dinamakan hukum tetapi disebut norma. Keempat, Sumber positivisme hukum yang terbagi dalam hukum material dan formal juga memiliki aspek perbedaan dengan hukum Islam. Sumber hukum material merupakan materi- materi hukum berupa perilaku dan realitas yang ada di masyarakat. Sedangkan sumber hukum formil adalah 1) Undang-undang, 2) Kebiasaan, 3) Yurisprudensi, 4) Traktat, dan 5) Doktrin. Sementara Hukum Islam juga mempunyai sumber hukum material, namun memiliki substansi berbeda dengan positivisme, yaitu bahwa sumber hukum Islam berasal dari wahyu, sedangkan hukum positif bersumber kepada perilaku dan realitas dalam masyarakat.
Kitab Al-Risa<lah Dalam Tilikan Positivisme Hukum 17 Kodikasia, Volume, 12 No. 1 Tahun 2018 DAFTAR RUJUKAN Ali, Achmad, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Jakarta: Kencana, 2012. al-Sah{a>ri<, ‘Abdulla>h bin Sa’i<d Muh}ammad ‘Abba>di< al-Lah{ji<, I<d}a>h al-Qawa>’id al-Fiqhi<yah, Surabaya: al-Hidayah, 1410 H. al-Sha>fi’i, Muh}ammad bin Idri>s, Ar-Risa>lah al-Ima>m al-Sha>fi’i. terj. Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008. al-Sha>fi’i<, Muh}ammad bin Idri>s, al-Risa>lah ed. Ah}mad Muh}ammad Sha>kir, T.t: Da>r al-Fikr, t.t. Armia, Muhammad Siddiq Tgk., Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008. Basuki, Cara Mudah Menyusun Proposal Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2011. Faruki, Kemal A., Islamic Jurisprudence, Delhi: Adam Publisher & Distributors, 1994. Fuadi, Munir, Teori-Teori Besar Dalam Hukum, Jakarta: kencana, 2013. Hasan, Ahmad, “Al-Sha>fi’i<’s Role in the Development of Islamic Jurisprudence,” Islamic Studies, 5 (1966). Ibrahim, Johnny, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, 2006. Irianto, Sulistyowati, dkk., Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Buku Obor, 2013. Koesnoe, Moch., Kritik terhadap Ilmu Hukum, Yogyakarta: Lembaga Riset dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum UII, 1981. Mastuhu (ed.), Metodologi Penelitian Agama, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006. Nawawi, Hadari & Mimi Martini, Penelitian Terapan, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996. Noeng, Muhajir, Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2011. Nyazee, Imran Ahsan Khan, Theories of Islamic Law, Islamabad: The International Institute of Islamic Thought, 1994. Praja, Juhaya S., Aliran-Aliran Filsafat dan Etika. cet. Ke-2. Jakarta: Kencana, 2005. Raharjo, Satjipto, Buku Materi Pokok Pengantar Ilmu Hukum Bagian IV, Jakarta: Karunika, 1985. Rhiti, Hyronimus, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Sampai Postmoderisme), Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2011. Saleh, Abdul Mun’im, Otoritas Maslahah dalam Madhhab Syafi’I, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2012. Surajiyo, Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara, 2013. Susanto, Anthon F., Ilmu hukum Non Sistemik; Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010. Tanya, Bernard L. dkk., Teori Hukum. Yogyakarta: Genta Publishing. 2010. Usman, Sabian, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
18 Abdul Mun’im, Lukman Santoso, Niswatul Hidayati Kodikasia, Volume, 12 No. 1 Tahun 2018 Wignjosobroto, Soetandyo, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Jakarta: Elsam & Huma, 2002. Yasid, Abu, Aspek-Aspek Penelitian Hukum, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010. Yasid, Abu, “Paradigma Tradisionalisme dan Rasionalisme Hukum dalam Perspektif Filsafat Ilmu,” Jurnal hukum No. 4 vol. 17 Oktober 2010. |

Pos Terkait
Periklanan
BERITA TERKINI
Toplist Popular
#2
#4
#6
#8
Periklanan
Terpopuler
Periklanan
Tentang Kami
Dukungan

Copyright © 2024 idkuu.com Inc.