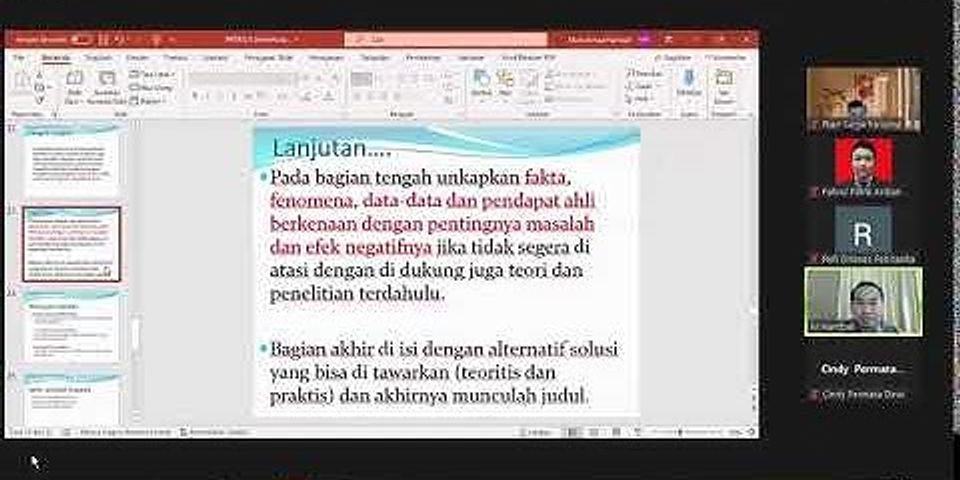Logika dasar dalam sistem politik yang demokratis mengasumsikan bahwa kekuasaan terletak di tangan rakyat. Untuk membentuk dan menyelenggarakan pemerintahan, rakyat kemudian memilih wakil-wakilnya melalui pemilihan umum. Sesuai logika ini, karena wakil (para politikus) yang terpilih ini adalah wakil rakyat yang kemudian duduk di parlemen, kekuasaan yang berada di tangan rakyat tadi dapat pula diartikan sebagai kekuasaan yang dipegang para politikus yang duduk di parlemen tersebut. Setelah Perang Dunia II, negara-negara fasis dan militeristik seperti Italia, Jerman, dan Jepang pun akhirnya menganut prinsip di atas. Jerman dan Jepang yang di masa lalu dikenal sebagai pemilik kekuatan militer yang tangguh serta sekaligus sebagai negara penganut paham militer pun terpaksa atau dipaksa membubarkan tentaranya. Jerman, misalnya, membentuk kekuatan militer baru yang ikatan historisnya terputus dari tentara lama yang terbiasa mencampuri urusan politik, sementara Jepang membentuk Pasukan Bela Diri (Self Defense Force,SDF) dan sampai hari ini tidak pernah membentuk tentara lagi. Berkat langkah di atas, Jepang dan Jerman berhasil menyejajarkan diri dengan negara-negara demokrasi yang telah maju lebih dulu dan menjadi negara di mana supremasi sipil mengedepan. Kalahnya Jerman dan Jepang dalam Perang Dunia II yang kemudian melahirkan citra buruk militer di pentas politik telah melicinkan jalan bagi berakhirnya popularitas dan kekuasaan militer dalam kehidupan politik di negeri itu. Berakhirnya era kekuasaan militer di atas disambut gembira masyarakat di dalam negeri dan dunia internasional. Militer yang merupakan warga negara istimewa karena mempunyai lisensi untuk membunuh serta merupakan institusi yang sah dalam monopoli penggunaan kekerasan --dan hubungan organisasinya diatur dalam pola hierarki atasan-bawahan serta bergerak atas jalur komando-- dianggap sebagai institusi yang menurut kodratnya tidak demokratis dan memang tidak boleh demokratis. Jika jalur komando dalam mata rantai hierarki serta sikap taat dan patuh dalam disiplin tentara dihilangkan, tentara bahkan tidak lagi akan disebut sebagai tentara. Namun, tidak demokratisnya organisasi tentara tidaklah berarti tentara adalah institusi yang buruk, melainkan organisasi tentara adalah institusi yang tidak cocok untuk berada di pentas kehidupan politik yang demokratis. Anggapan bahwa tentara tidak cocok berada di pentas politik sebenarnya juga berlaku di Indonesia pada masa awal kemerdekaannya. Sekalipun keinginan tentara untuk terlibat dalam kehidupan politik praktis mulai terlihat secara lebih nyata ketika Jenderal Nasution menggagas ide dwifungsi pada tahun 1950-an, selama periode kemerdekaan, periode demokrasi liberal sampai masa Demokrasi Terpimpin, tentara tidak secara amat nyata menjalankan pemerintahan. Namun sejak zaman Orde Baru, situasi ini mengalami perubahan yang drastis. Berbeda dengan Jerman dan Jepang yang kalah perang,tentara Indonesia melakukan semacam klaim historis bahwa mereka memiliki andil besar,terutama dalam perang kemerdekaan. Selama 32 tahun Presiden Suharto berkuasa, tentara bahkan menjadi yang terdepan dalam pentas politik praktis sehingga menjadi guardian of the state tak hanya pada masa perang, tetapi juga pada masa damai. Dalam suasana dunia yang telah semakin mengedepankan supremasi sipil sekarang ini, pertanyaannya adalah bagaimanakah sebaiknya penataan dan pendefinisian kembali peran militer ini dilakukan? Seiring jatuhnya pemerintahan Suharto dan bermulanya era Reformasi, gerakan agar tentara tidak berada di pentas politik praktis mulai dijalankan. Hilangnya Fraksi ABRI di DPR merupakan sebuah tonggak yang penting. Tapi kemudian, apa lanjutannya? Jika saja yang diinginkan adalah tegaknya supremasi sipil, bagaimanakah wujudnya? Dalam pemikiran sipil, supremasi sipil cenderung diartikan sebagai dominasi sipil atas militer.Alasannya, jika dibalik menjadi dominasi militer atas sipil, hal ini melawan alam pikiran demokrasi. Meski begitu, dari sisi militer (terutama sejak kejayaannya di pentas politik Orde Baru), dominasi sipil terhadap militer bukanlah masalah yang dapat diterima begitu saja. Mungkin atas dasar pengalaman bahwa dominasi militer terhadap sipil cenderung memberikan bukti bahwa sipil dipolitisasi militer, dalam dominasi sipil atas militer pun muncul kekhawatiran bahwa militer akan dipolitisasi oleh sipil. Sebagai solusi dari persoalan mendominasi dan didominasi di atas, kini sipil dan militer tampak berusaha mencapai titik keseimbangan melalui kompromi.Posisi Menteri Pertahanan (Menhan) yang dijabat sipil dan posisi Panglima TNI (militer) yang sejajar dengan Menhan adalah bukti kompromi ini. Dalam pola ini,tidak ada ordinat dan tidak ada subordinat, tidak ada yang memerintah dan tidak ada yang diperintah. Yang ada adalah koordinasi antara Menhan yang sipil dan Panglima TNI yang tentara. Dalam pola ini supremasi sipil dan supremasi militer cenderung dikesampingkan dan supremasi hukum kemudian muncul sebagai konsep yang diharapkan dapat menggantikannya. Apakah hal di atas memang ideal? Terhadap pertanyaan ini, penilaian tiap orang mungkin saja berbeda. Akan tetapi, suatu hal yang jelas adalah jika supremasi sipil dipandang perlu diwujudkan,munculnya politikus- politikus sipil yang tangguh serta memiliki integritas kepribadian yang tinggi yang akan mewarnai Dewan Perwakilan Rakyat (dan mewarnai kabinet) jelas diperlukan. Termasuk dalam pengertian di atas adalah munculnya partai politik yang betul-betul kuat, profesional, dan merupakan organisasi mapan sebagaimana halnya organisasi TNI yang tetap berjalan dengan baik tanpa bergantung pada ketokohan atau pada siapa yang memimpinnya. Dalam kaitan ini, tentu amat diharapkan pula jika organisasi-organisasi sipil lain sanggup tumbuh menjadi wadah yang kuat serta sanggup menyelesaikan berbagai persoalan. Sebagai misal, mencegah dan menyelesaikan konflik antarsipil, entah konflik atas dasar isu agama, suku atau lainnya. Jika kita berasumsi bahwa insting guardian of the state telah membuat tentara ragu untuk tunduk pada supremasi sipil, terutama karena sipil kurang meyakinkan bahwa dirinya memang sanggup mengendalikan negara,kesan tidak sanggupnya sipil ini tentu akan semakin mendorong dan bahkan menjadi justifikasi bagi keengganan atau keraguan tentara tadi. Dalam masalah tegaknya supremasi sipil,tampaknya hanya jika sipil betul-betul siap dan memiliki kemampuan sajalah peran dan kekuasaan militer di pentas politik dapat dikurangi secara bertahap sehingga supremasi sipil akhirnya dapat ditegakkan. Sebaliknya, sejauh organisasi sipil (termasuk partai politik) lemah dan hanya mengandalkan kekuatan figur atau tokoh, sejauh itu pulalah jauhnya jarak bagi tegaknya supremasi sipil tadi. Jika kuat, dewasa,dan mapannya organisasi sipil dipandang sebagai sebuah syarat atau kewajiban, sedangkan tegaknya supremasi sipil adalah hak yang dinilai sipil sebagai miliknya, maka sanggupkah sipil memenuhi syarat atau kewajiban tadi, di luar sekadar menuntut haknya? Hal di atas tentu harus menjadi renungan dan sekaligus pertanyaan yang harus dijawab terutama oleh sipil,juga oleh kita semua.(*) Yusron Ihza Mahendra Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bidang Pertahanan (ahm) |

Pos Terkait
Periklanan
BERITA TERKINI
Toplist Popular
#2
#4
#6
#8
Periklanan
Terpopuler
Periklanan
Tentang Kami
Dukungan

Copyright © 2024 idkuu.com Inc.